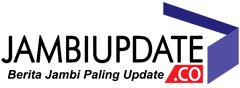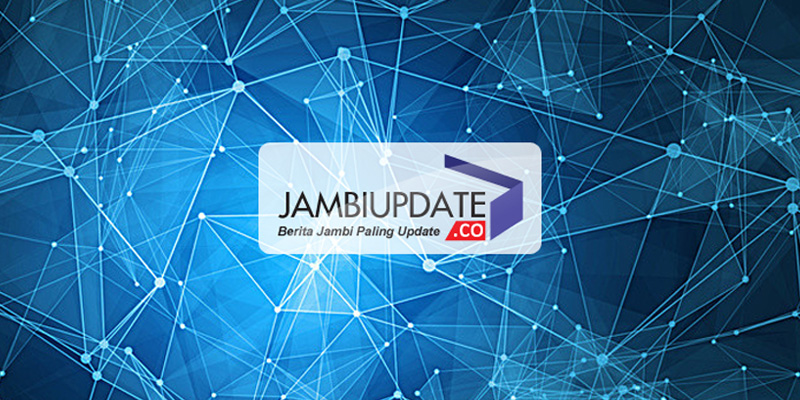JABATAN kepemimpinan dalam Islam adalah amanah, bukan nikmat. Karenanya,harus dipertanggung jawabkan bukan saja kepada atasan dan rakyat di dunia ini, tapi juga dipertanggung jawabkan kepada Allah Tuhan Pengatur Alam semesta ini di akhirat kelak.
Karena jabatan itu amanah, maka tak heran jika generasi salafush-shalih dalam menyikapi jabatan itu sangat hati-hati bahkan kalau bisa mereka menolak untuk menjadi seorang pemimpin atau pejabat negara. Dan jika akhirnya mereka ‘dipaksa’ harus menerima beban amanah kekuasaan, mereka begitu takut dihisab oleh Allah SWT pada Hari Kiamat nanti.
Inilah yang tergambar dari ucapan Khalifah Umar bin Khathab ra.:”Seandainya ada seekor keledai terporosok di Kota Baghdad karena jalan rusak, aku sangat khawatir Allah SWT akan meminta tanggung jawabku di Akhirat nanti”.
Sikap kehati-hatian itu juga tercermin pada diri Khalifah Umar bin Abdul Aziz (cicit Khalifah Umar bin Khathab). Sesaat setelah Khalifah dari Bani Umayah ini dilantik sebagai Khalifah/Kepala Negara, kalimat pertama yang ia ucapkan bukannya “alhamdulillah” karena bersyukur atas jabatannya, tapi justru ia ucapkan kalimat “Innalillah Wainnaa ilaihi raaji’un”, Suatu ungkapan kegelisahan dan kesedihan dari seorang Muslim yang diserahi amanah kekuasaan oleh rakyatnya.
Umar bin Abdul Aziz itu menyadari betul sabda Baginda Nabi saw :” Sesungguhnya kekuasaan itu amanah, pada Hari Kiamat nanti ia akan berubah menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengambilnya dengan haq dan menunaikan apa yang diamanahkan di dalamnya”.( HR.Muslim). Dan sabda Nabi ini adalah nasihat Nabi kepada salah seorang shahabatnya, Abu Dzar al-Ghifari yang usul minta jabatan kepada Nabi. Tapi sayang, Nabi tidak mengabulkannya, karena Abu Dzar dianggap tidak masuk kriteria Nabi sebagai pemimpin. Karena, Abu Dzar dianggap ambisius terhadap jabatan.
Nasihat Nabi diatas bukan hanya untuk Abu Dzar tapi untuk seluruh umatnya. Nadanya seperti mengancam, tapi seorang Nabi peduli pada umatnya itu sedang mewanti-wanti. Ada tiga kriteria pejabat atau pemimpin yang tersembunyi dalam pesan diatas, yaitu amanah, mengambil dengan benar dan menunaikan dengan baik.
Kriteria diatas tidaklah sederhana. Sebab, pemimpin dalam gambaran Nabi adalah pekerja bagi orang banyak, bukan sekadar penguasa.Dan pekerja seperti digambarkan oleh al-Qur’an haruslah orang kuat dan amanah.”Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja, ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. QS.al-Qashash : 26.
--batas--
Kuat pada ayat diatas adalah kuat bekerja dalam memimpin. Sedang maksud amanah adalah tidak berkhianat dan tidak menyimpang, dengan motif karena takut kepada Allah SWT. Maka sebagai pekerja untuk umat, sifat kuat bekerja adalah prasyarat penting pemimpin. Tapi, yang lebih penting lagi adalah menjaga sifat amanah yang bisa hilang karena tuntutan pekerjaannya.(Yusuf Qaradhawi,al-Siyasah al-Syar’iyyah Fi Dhaui Nushus al-Syari’ah wa Maqashiduha).
Nabi pun konsisten dengan kriterianya. Khalid bin Walid dan ‘Amr bin ‘Ash yang baru masuk Islam diberi jabatan pimpinan militer. Padahal, ilmu keislaman mereka berdua belum memadai.Tapi ternyata, keduanya dianggap kuat bekerja dan mampu menjaga amanah. Sebaliknya, orang sealim Abu Hurairah yang sangat kuat hafalan hadisnya dan banyak mendampingi Rasulullah tidak diberi jabatan apa-apa. Semangat Hasan bin Tsabit membela Islam juga tidak masuk kriteria pemimpin yang dicanangkan Nabi.
Masalahnya, seseorang bisa gagal menunaikan tugas kepemimpinannya karena tidak mampu mempertahankan amanah (khiyanat) atau karena tidak ada ilmu untuk itu (jahil). Maka,al-Qur’an memberi pelajaran dari kisah Nabi Yusuf. Disitu dikisahkan bahwa ia diberi kedudukan tinggi oleh raja karena dapat dipercaya(amin), pandai menjaga (hafiz), dan berpengetahuan(alim) (QS.Yusuf :54-55). Ini berarti kriteria kepemimpinan ditambah satu syarat lagi, yaitu hafiz artinya menjaga amanah. Hal ini disinggung Nabi dalam hadis yang lain,”Sesungguhnya Allah akan menanyai setiap pemimpin tentang rakyatnya, apakah menjaganya (hafiz) atau menyia-nyiakannya”.(HR.Nasa’i dan Ibnu Hibban).
Syarat yang satu lagi adalah sifat al-‘Alim. Artinya mengetahui apa yang menjadi tanggung jawabnya, mengetahui ilmu tentang tugasnya. Adalah malapetaka suatu bangsa jika pemimpin yang dipilih dan dipercaya rakyat ternyata tidak cukup ilmu tentang tugasnya. Inilah yang diwanti-wanti Umar bin Khathab bahwa “amal tanpa ilmu itu lebih banyak merusak dari pada memperbaiki”.
Ringkasnya, pemimpin atau pejabat Muslim yang sesuai dengan ajaran Islam adalah yang bersifat amanah,memperolehnya dengan benar, menunaikan dengan baik, kuat, dapat dipercaya (amin), pandai menjaga (hafiz) amanahnya, dan berpengetahuan (alim) tentang tugas kepemimpinannya.
Dari kriteria diatas, tampaknya Nabi tidak mengisyaratkan bahwa pemimpin Muslim itu harus seorang yang tinggi ilmunya dalam bidang agama. Seorang Muslim dengan kekuatan leadership dan amanahnya bisa menduduki jabatan tertinggi meski ilmu agamanya tidak setingkat Ulama. Ini pulalah yang disimpulkan oleh Yusuf al-Qaradhawi. Namun, tidak berarti orang yang buta agama atau bahkan yang sekuler-liberal bisa masuk dalam kriteria Nabi diatas. Sebab, seseorang tidak akan amanah jika ia tidak memahami syariah.
Pemimpin yang tidak tahu agama bisa lepas dari Tuhannya atau jauh dari masyarakatnya. Sebab, seorang pemimpin (amir/imam) memiliki dua tugas, yakni beribadah kepada Allah dan berkhidmat kepada masyarakat. Untuk beribadah diperlukan ilmu dan iman, untuk berkhidmat diperlukan ilmu untuk menyejahterahkan rakyat. Oleh sebab, “Pemimpin yang tidak berusaha meningkatkan materi dan akhlak serta kesejahteraan rakyat tidak akan masuk surga”.(HR.Bukhari).
Kriteria pemimpin (amir/imam) yang dicanangknan Nabi dan ditambah dengan kriteria dari al-Qur’an itu diterjemahkan oleh al-Mawardi dalam al-Ahkam al-Sulthaniyah menjadi enam. Enam kriteria itu adalah berperilaku adil, memiliki ilmu untuk mengambil keputusan,panca indra yang sehat (khususnya alat dengar, melihat, dan alat bicara), sehat secara fisik dan tidak cacat, peduli terhadap berbagai masalah, dan terakhir tegas serta percaya diri.
Namun, kriteria-kriteria diatas secara amali (praxis) berkulminasi pada dua sikap nurani, yaitu pemimpin yang mencintai dan dicintai; yang mendoakan dan didoakan rakyat. Bukan pemimpin yang dibenci dan dikutuk rakyat (HR Muslim). Tapi, bagaimana akan mencintai rakyat jika pemimpin itu lebih cinta jabatan dan partai politiknya ?.
Pertanyaannya, bisakah pemimpin produk sistem demokrasi dapat menelorkan pemimpin tangguh yang amanah ?. Sangat sulit !. Karena, jabatan pemimpin atau Presiden/Kepala Daerah dalam sistem demokrasi itu cenderung berorientasi pada kekuasaan, bukan pengabdian dan ibadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, solusinya ya kita taat dan tunduk kepada syariah Allah SWT,Islam!. Insya Allah, Negara yang kita cita-citakan yakni “baldatun thayyibatun warobbun ghofur” akan terealisir, Amin !
Penulis adalah Pemerhati Sosial Keagamaan.
Sumber : Jambi Ekspres