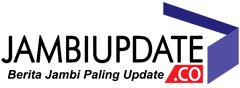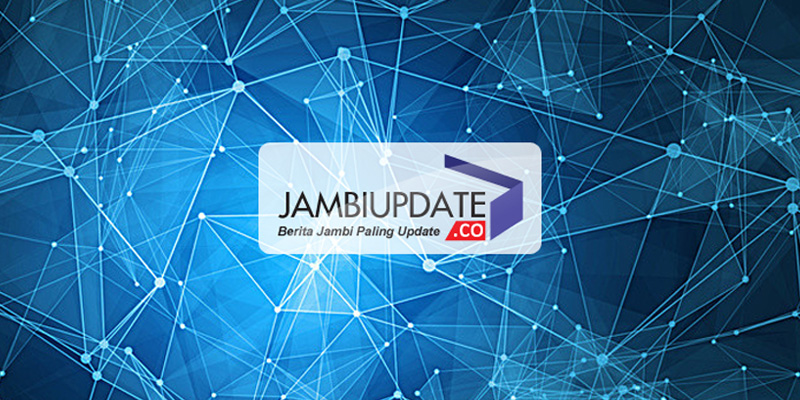Apapun program pemerintah tentang Ujian Nasional (UN) pastilah muncul pro-kontra. Nampaknya UN ‘belum’ menjadi instrument untuk ‘mempersatukan’ bangsa. Karena itu, untuk menyatukan persepsi masyarakat tentang UN, Kemdikbud mengelar konvensi UN dalam rangka menerima masukan dari mayarakat atas penyelenggarakan UN dan didahulu dengan prakonvensi di tiga kota: Medan, Denpasar dan Makasar.
Konvensi UN digelar di Gedung Kemdikbud, Jakarta selama dua hari, 26-27 September 2013, serta dihadiri sedikitnya 350 peserta yang memiliki kepentingan dan peduli dengan pendidikan nasional yang terdiri dari guru dan kepala sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah negeri dan swasta, LSM pendidikan dan masyarakat peduli pendidikan, dewan pendidikan dan komite sekolah, serta asosiasi yang bergerak di bidang pendidikan. Di samping itu, konvensi dihadiri perwakilan dinas pendidikan dan dinas agama baik di tingkat pusat, provinsi, serta kabupaten/kota. (Kemdikbud)
Ada 17 point hasil konvesi ini yang terpusat pada: manajemen UN dan penentu kelulusan (Kemdikbud). Inti dari konvensi ini adalah ‘apapun kata orang’ UN tetap dilaksanakan. Dianalisis, ternyata ada beberapa poin yang berbeda dengan penyelenggarakan UN tahun sebelumnya: (1) pengandaan dan distribusi soal dilaksanakan provinsi dengan pengawasan pemerintah pusat dan PTN dan PTS; (2) ketika ada force major, penundaan pelaksanaan UN harus dilakukan secara nasional; (3) peran provinsi, dinas pendidikan dan Kanwil Kementerian Agama dalam UN meliputi penyiapan bahan, pelaksanaan, termasuk distribusi UN, penggandaan, pemindaian dan skoring; (4) nilai rapor harus dikirim setiap semester dan pengiriman dilakukan secara daring (on-line); (5) Kelulusan UN ditentukan berdasarkan rasio 60% nilai UN dan 40% nilai sekolah. Komposisi nilai sekolah terdiri atas 70% nilai rapor dan 30% ujian sekolah.; (6) UN mengukur ranah kognitif yang lebih tinggi (higher order thinking).
Untuk itu, setiap soal diberi bobot berdasarkan pada tingkat kesulitan dan kompleksitas kompetensi yang diukur, dan rasio kelulusan menjadi 100% ujian sekolah dan 100% UN. Hal ini berarti bahwa setiap siswa yang akan mengikuti ujian nasional harus lulus ujian sekolah terlebih dahulu.
Bisa diterima hasil konvensi ini dengan catatan: Pertama, peserta konvensi terdiri dari praktisi pendidikan. Rektor, dosen, Kepala Dinas pendidikan propinsi dan Kabupaten, pengawas, guru dan masyarakat yang ‘notabene’ merupakan ‘bawahan’ Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sudah ‘bisa dipastikan’ ‘orang-orang ini’ tidak akan berani melawan atasan dengan menolak UN. Kalau tidak ‘jabatan’ adalah taruhannya. Pastilah mereka mengambil ‘langkah aman’.
Kedua, penyelengaraan UN merupakan kajian akademik, padahal dalam satu kesempatan Mendikbud mengatakan bahwa pemerintah menyelenggarakan UN untuk menjalankan Undang-undang (UU). PP Nomor 32 Tahun 2013 sebagai pengganti PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menjadi dasar pelaksanaan UN sebagi turunan pelaksanaan teknis dari UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. PP-nya belum dicabut, justru pemerintah salah kalau tidak melaksanakan UN apalagi PP-nya masih ada. Kalau hanya ‘menjalankan UU belum bisa dikata kegiatan itu merupakan kajian akademik karena pembuatan UU adalah proses politik (suara terbanyak). Kalau UU itu ‘jelek’, tapi didukung oleh banyak ‘suara’, maka UU itu akan disahkan begitu juga sebaliknya kalau UU itu bagus secara akademik, tapi tidak didukung oleh banyak ‘suara’ pastilah UU tidak akan disahkan.
Ketiga, kalau memang UN itu hasil kajian akademik, kenapa dalam konvensi ini, keynote speaker-nya adalah seorang politisi, Mantan Wapres, Jusuf Kalla. Dan tentu saja, padangan JK terfokus pada kajian politik bukan akademik. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan bahwa Ujian Nasional (UN) dapat menggenjot semangat siswa untuk belajar. Apa betul JK pernah meneliti secara ilmiah motivasi siswa sampai masyarakat ‘kecil’?
Keempat, pemerintah mengatakan bahwa UN itu memotivasi siswa untuk belajar. Kalau pernyataan ini betul. Pertanyaan adalah apakah motivasi ‘tinggi’ ini untuk mendapatkan nilai atau untuk lulus UN. Dan pemerintah harus mencari tahu kapan ‘pergerakan’ motivasi tinggi siswa mulai naik, pasti menjelang UN. Akibat ‘ketinggian’ motivasi, orang tua siswa ‘tidak percaya’ dengan sekolah, mereka ‘berlomba-lomba’ mengkursus anak anak mereka di Bimbel. Akibatnya, siswa dari keluarga miskin ‘hanya’ gigit jari.
Kelima, disayangkan konvensi ini tidak mengundang ‘aktor utama UN’: mantan siswa yang telah mengikuti UN baik yang lulus maupun yang tidak lulus untuk mendengarkan ‘kenikmatan’ mereka dalam mempersiapkan diri menghadapi UN. Dan apa yang melandasi mereka sehingga motivasi mereka ‘melenjit tinggi’ menjelang UN.
Keenam, idealnya Kepala sekolah yang 100% gagal meluluskan siswanya dan guru yang mata pelajarannya ‘penyumbang’ kegagalan siswa juga ‘menjadi perhatian’ untuk mendapatkan informasi ‘efek domino’ dari kegagalan siswa dalam UN.
Dari pada ‘bertengkar terus’, pemerintah ideal memberi kesempatan kepada sekolah untuk menyelenggarakan secara independen (baca-moratotium UN) dan membandingkan hasilnya dengan hasil UN format sekarang. Diprediksi hasilnya: (1) tidak ada guru yang ‘berani’ memberi nilai 10 dan hanya segelintir guru yang akan memberi nilai 9; (2) nilai siswa dikisaran 5-8; (3) ‘banyak’ siswa yang tidak lulus karena mereka ‘wajar’ tidak lulus; (4) guru akan ‘lebih dihormati’; (5) sekolah akan lebih terfokus pada proses pembelajaran; (6) ‘kejujuran hakiki’ akan muncul; (7) tidak ada ‘surprise’: yang rajin nilainya tinggi, yang malas nilainya rendah.
Tidak ada yang melarang UN digelar, tapi ...
*) Pemerhati Pendidikan, Guru MAN Muara Bulian, Anggota PELANTA