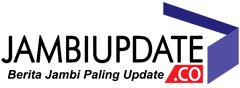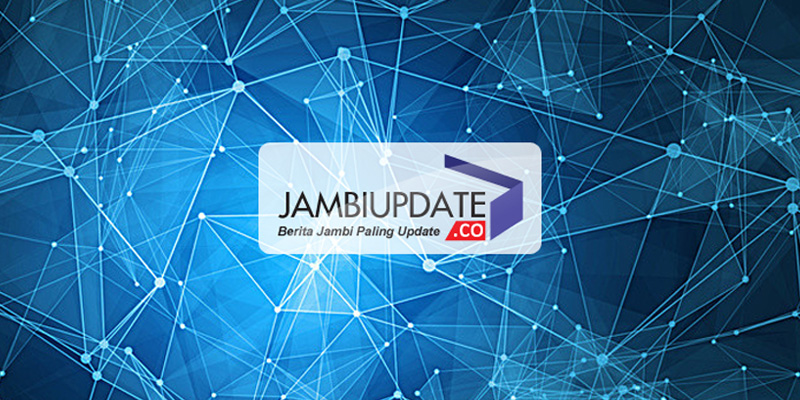MEMBACA artikel di Jambi Ekspres, 22 Oktober 2013 dengan judul Politik Indonesia dan Peluang Bagi Perempuan yang ditulis oleh Nona Wenny, - sapaan saya untuk penulis - , saya tergelitik juga untuk menulis sebuah perspektif yang berbeda. Sebagai sebuah realitas politik yang didukung legislasi, aksi afirmasi -affirmative action- untuk perempuan di lembaga legisatif saya pikir perlu selalu diperbincangan. Selain itu, juga dievaluasi dampaknya serta ditilik kesesuaiannya dengan perkembangan sosial budaya masyarakat. Lebih dari itu, implementasi aksi afirmasi pada era otonomi daerah saya pikir perlu mempertimbangkan kondisi sosiologis dan antropologis masing-masing daerah.
Sejak pertama kali aksi afirmasi 30 % caleg perempuan diterapkan melalui Pasal 65 (1) UU RI no. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, saya termasuk orang yang tidak begitu sepakat dengan pasal tersebut. Baiklah saya uraikan beberapa pemikiran yang menurut saya sampai akhir ini masih tetap perlu dijawab dengan ilmiah.
Pertama, seberapa pentingkah “banyak perempuan” duduk di lembaga formal politik semacam DPR/DPD? Adalah hak setiap manusia untuk beraktivitas sesuai dengan minat dan kemampuannya termasuk dalam bidang politik praktis. Tapi mengharapkan lembaga legislatif diisi minimal 30 % perempuan tentu harus dilihat apa urgensinya. Sebagian besar alasan pendukung aksi afirmasi adalah agar kepentingan kaum perempuan dan tema-tema sosial lainnya mendapat perhatian layak dalam proses legislasi di negeri ini. Fakta menunjukkan bahwa keberadaan kaum perempuan di legislatif sejak reformasi secara umum belum menunjukkan kinerja yang memuaskan sesuai dengan yang diharapkan. Kalau mau disebut, undang-undang atau Perda apa saja yang benar-benar hasil perjuangan kaum perempuan? Ada perumusan UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Anti Pornograafi yang sempat mencuri perhatian banyak kalangan, karena cukup menonjolkan peran kaum perempuan di DPR. Tapi, alih-alih mendapat simpati dari gerakan perempuan secara makro, malah sebagian gerakan perempuan yang beraliran feminis sekaligus pendukung aksi afirmasi, justeru menjadi penentang RUU tersebut sebelum akhirnya disyahkan.
Opini-opini yang justeru banyak beredar menunjukkan bahwa keberadaan perempuan di lembaga legislatif belum menunjukkan pengaruh signifikan terhadap isu-isu perempuan dan permasalahan sosial lainnya. Padahal, seperti diurai dalam tulisan Nona Wenny, keberadaan perempuan di kancah institusi politik tersebut memiliki konsekuensi tidak sederhana dalam hidup pribadi dan sosialnya. Apalagi, kapasitas perempuan dalam dunia politik memang belum memadai. Maka masalahnya adalah pada “kapasitas”, bukan “banyaknya”. Tanpa bermaksud meremehkan kemampuan perempuan, saya menilai tidak semua perempuan sesuai dengan dunia politik praktis, khususnya dengan budaya politik Indonesia saat ini. Oleh karena itu, pendekatan terhadap peningkatan kuantitas saya pikir justeru salah arah dalam upaya membangun kebijakan publik yang ramah perempuan dan masalah sosial lainnya. Kebijakan aksi afirmasi keterwakilan 30 % tersebut justeru memaksakan kaum perempuan untuk masuk dunia yang belum tentu sesuai dengan nalurinya, dan selanjutnya menjadi pemubaziran sumber daya kampanye. Padahal, akses perempuan terhadap sumber daya untuk membiayai kampanye saja masih sangat terbatas. Kenapa peluang-peluang dukungan penguatan perempuan seperti ini tidak dialihkan saja kepada aspek-aspek yang lebih penting, semacam dukungan pendidikan tinggi untuk perempuan, atau dukungan fasiltas kerja ramah perempuan? Inilah harga mahal demokrasi; Pemilu.
Kedua, jika pun aksi afirmasi dimaksudkan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif, seberapa efektifkah aturan 30 % caleg harus perempuan untuk tujuan tersebut? Jumlah kursi yang diperoleh perempuan pada periode 2004- 2009 hanya 11,6 % di DPR sedangkan di DPD sebesar 19,8 %. Dibanding dengan periode pertama Pemilu setelah reformasi, jumlah kursi yang diperoleh perempuan memang meningkat dari hanya berjumlah 9,9 %. Namun, justeru jumlah tersebut menurun jika dilihat dari masa Orde Baru yang tidak mengenal aksi afirmasi yaitu berjumlah 12 % pada Pemilu 1992. Untuk menguatkan aksi afirmasi, UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD sebagai pengganti undang-undang sebelumnya menambah aturan afirmasi di KPU, PPK, Bawaslu bahkan pembentukan kepengurusan partai politik, semua harus memperhatikan keterwakilan perempuan. Hasilnya, pada Pemilu 2009, perempuan memperoleh kursi sejumlah lebih 18 %.
Kebijakan aksi afirmasi keterwakilan 30 % ini tidak memiliki akar argumentasi yang kuat. Jika asumsinya adalah selama ini kesempatan politik kaum perempuan berada pada subordinasi laki-laki sehingga perlu perlakukan khusus, adalah lebih tepat jika sistem pemilihannya juga mendapat perlakuan khsus sehingga tujuan “banyak perempuan” di legislatif itu benar-benar terwujud. Mislanya, pemilihan caleg dibagi 2 kategori untuk calon laki-laki dan perempuan. Bahkan jika 30 % perempuan di legislatif tercapai pun, dalam sistem demokrasi juga tidak terlalu signifikan keberadaannya. Contoh sederhana, jika dalam sebuah usulan adanya cuti haidh bagi perempuan dalam RUU ketenaga-kerjaan, 30 % anggota DPR perempuan setuju, tapi laki-laki tidak setuju dengan berbagai alasan, maka keputusan tetap akan menolak. Artinya, keberaadaan perempuan di legislatif hanya diarahkan pada batas pelengkap atau pengusung ide.
Maka, kembali kepada pertanyaan pertama, seberapa pentingkah “banyak perempuan” itu di legislatif? Belajar pada kiprah perempuan-perempuan politik -untuk menyebut mereka yang memang memiliki kapasitas politik yang baik, mereka hadir dan mejadi fenomenal dengan mengandalkan kapasitas pribadi. Kapasitas yang tumbuh melalui sebuah proses pendidikan serta pembiasaan dalam lingkungan sosialnya, bisa jadi keluarga, sekolah, organisasi, atau pergerakan yang mereka ikuti. Kebanyakan dari mereka, juga hidup dalam lingkungan sosial-budaya yang “dianggap” kental dengan subordinasi laki-laki. Bahkan, sebagian mereka menjadi tokoh-tokoh politik di usia sangat muda. Sebut saja Bashaeer Othman, yang berani mewakili kaum muda memimpin Kota Allar-Palestina selama 2 bulan dalam usia 16 tahun, atau Atifete Jahjaga yang merupakan presiden perempuan termuda dengan menduduki kursi presiden Kosovo dalam usia baru 36 tahun. Ada juga Corazon Aquino yang menjadi Presiden Filipina lebih dari 6 tahun, Chandrika Kumaratunga menjadi Presiden Sri Langka lebih 11 tahun dan masih banyak lainnya. Terlepas dari pro-kontra model dan capaian kepemimpinan mereka, ternyata mereka adalah sebagian dari perempuan-perempuan yang memang memiliki kapasitas di dunia politik. Mereka tumbuh dengan alami, tanpa desain aksi afirmasi.
Ketimbang memperjuangkan “banyak perempuan” di lembaga legislatif dengan sistem Pemilu yang biasa saja, membicarakan optimalisasi posisi tawar perempuan di luar parlemen -extra parliamentary- lebih menarik. Meskipun sebelumnya saya mengatakan tidak semua perempuan sesuai masuk dalam dunia politik praktis, tapi perempuan memiliki posisi tawar yang tinggi dalam politik. Besarnya potensi yang dimiliki oleh perempuan ini disadari betul oleh penguasa Orde Baru. Menurut saya, inilah mengapa Orde Baru sangat memperhatikan pengorganisasian perempuan di bawah kontrol pemerintah. Dengan dalih pemberdayaan perempuan, Dharma Wanita dan kegiatan PKK telah dijadikan salah satu alat penguasa Orde Baru untuk menyosialisasikan dan menyukseskan agenda-agenda pemerintah.
Selain media, perempuan memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam mempengaruhi peta dan budaya politik masyarakat. Selain jumlahnya yang besar, karakter umum perempuan itu mudah terpengaruh dan sebaliknya mudah mempengaruhi. Apalagi jika dikaitkan dengan ikatan emosional kelompok, perempuan pada saat-saat tertentu bisa menjadi sangat kompak.
Ditambah lagi kemampuan perempuan dalam menyebarkan informasi sudah teruji, bahkan melalui sarana paling tradisional, dari mulut ke mulut. Maka dalam politik, menurut saya ada 2 kelompok yang jangan sampai menjadi musuh; media dan perempuan. Melawan perempuan sama dengan melawan arus. Sebagai contoh, sudah banyak kaus jatuhnya popularitas seorang tokoh karena isu perselingkuhan atau pelecehan seksual. Tindakan seperti itu tidak diterima secara umum oleh perempuan.
Pada konteks inilah saya melihat penguatan peran politik perempuan lebih dibutuhkan dan lebih memungkinkan. Keberadaan organisasi-organisasi perempuan yang secara aktif memantau kebijakan pemerintah, mengampanyekan politik santun dan bersih serta memberi contoh hidup yang bebas KKN, akan lebih berpeluang memberikan kontribusi posisif bagi pembangunan sistem politik Indonesia sekaligus juga ramah terhadap perempuan itu sendiri.
Dalam model ini, kelompok perempuan bisa mengatur sendiri ritme gerakannya yang disesuaikan dengan tuntutan maupun dukungan lingkungan sosial-budaya setempat. Bagi masyarakat di daerah yang masih sangat kental dengan nilai-nilai tradisi dan agama, tuntutan peran perempuan dalam urusan kerumah-tanggaan sangat besar. Peran-peran extra parliamentary seperti ini jelas lebih mendapat dukungan dari masyarakat, sehingga akan mengurangi konflik interpersonal. Akhirnya saya menyimpulkan, untuk Indonesia masa sekarang, biarlah perempuan-perempuan yang berbakat memasuki institusi politik formal secara alami, dan di luar institusi politik formal itu, perempuan-perempuan lainnya berjuang dengan format yang berbeda.
(Dosen Ilmu Pemerintahan IAIN STS Jambi)