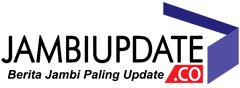DEBAR jantung jelang Ujian Nasional (UN) di sekolah/madrasah, bukan hanya dialami siswa, tapi orang tua ikut terguncang. Bahkan mungkin guru pun tak kalah risau ketika melihat murid mempertaruhkan masa depannya. Karena selama ini UN cenderung diresposisi bagai jihad besar dan sengaja didramatisir seolah-olah satu-satunya pintu sukses.
Padahal UN hanyalah aktivitas biasa yang tak berbeda dengan ujian harian. Perbedaannya hanya terletak pada teknis perhelatannya. Dimana semua lembar soal produk nasional, diangkut via pesawat, bungkusannya tersegel rahasia, dikawal polisi, dipagari pengawas, diiringi tim monitoring, dan dipublish media.
Jangan Dramatisir UN
UN yang tergolong proyek tahunan ini menempatkannya sebagai isu nasional. Betapa tidak ? Sorotan permasalahannya yang terjadi di lapangan lebih memiriskan. Karena kasus yang mengemuka ke pelataran publik hanya berkisar pada perihal contek-menyontek, kebocoran, kecurangan, jual beli kunci, hingga kontradiksi bangunan wacana sebagian pakar pendidikan yang mempertanyakan efektifitas UN.
Pemberitaan kasus UN tiap tahun tersebut, mengesankan seolah-olah UN dimata siswa adalah momen yang menyeramkan. Terlebih lagi perhelatannya melibatkan berbagai pihak termasuk aktifis yang ikut berkiprah memantau perkembangan lapangan. Bukan hanya itu, tapi politisasi UN pun tak kalah mencolok ketika pejabat berkunjung ke sekolah hanya untuk menggambarkan legitimasi helat UN yang aman terkendali.
Padahal, UN adalah domain keilmuan yang bersifat merdeka dan tak butuh popularitas publik. Dan idealnya yang terlibat cukuplah orang yang berkompeten saja. Sebab terlalu banyaknya kunjungan dari berbagai pihak seperti pejabat dengan alasan inspeksi atau apapun namanya.
Helat UN yang optimal, pihak penyelenggara harus bisa menghadirkan suasana yang kondusif untuk menjaga stabilitas mental anak dalam melakoni proses. Hal ini lebih utama, karena output UN hanya menawarkan dua akibat yaitu lulus atau gagal. Dan hal yang paling menakutkan lagi adalah ketika anak harus menerima kenyataan gagal, tentu guru dan orang tua sebagai orang paling bertanggung jawab dan bekerja ekstra untuk memulihkan kondisi psikis anak.
Dari dua kemungkinan itu, maka wajar kalau guru dan orang tua terkadang harus mengorbankan idealisme dengan menghalalkan segala cara demi sukses anak. Apalagi, UN sudah terlanjur disahkan sebagai satu-satunya instrumen kuantitatif untuk mengukur kualitas anak dalam menatap masa depannya.
Dari titik ini, pemerintah sebaiknya evaluasi dan reposisi kembali makna UN dengan menghadirkan konsep alternatif yang lebih menggambarkan unsur variabelitas kecerdasan anak secara utuh. Sebab jika hanya kepintaran mencontreng menjadi penentu tunggal, maka yang angka tersaji hanyalah gambaran kognisi, sedang potensi bakat, aktualisasi diri, kecerdasan sosial, ketahanan etika dan moralitas dinilai bukan domain yang menentukan. Jika demikian, maka UN hanya bisa meluluskan output kognisi dengan mengabaikan kebermaknaan nilai budaya, kearifan lokal dan pesan keluhuran bangsa.
Padahal bukankah tujuan pendidikan menurut UUD 1945 versi Amendemen terus menggiring output pendidikan untuk beriman, bertakwa, dan berahlak dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Jika semangat UU dibenturkan dengan realitas, sepertinya UN bukanlah instrumen yang menggambaran kualitas anak secara utuh.
Wallahu a’lam bissawaab
Penulis adalah Pemerhati Sosial, Staf Pengajar IAIN STS Jambi
Padahal UN hanyalah aktivitas biasa yang tak berbeda dengan ujian harian. Perbedaannya hanya terletak pada teknis perhelatannya. Dimana semua lembar soal produk nasional, diangkut via pesawat, bungkusannya tersegel rahasia, dikawal polisi, dipagari pengawas, diiringi tim monitoring, dan dipublish media.
Jangan Dramatisir UN
UN yang tergolong proyek tahunan ini menempatkannya sebagai isu nasional. Betapa tidak ? Sorotan permasalahannya yang terjadi di lapangan lebih memiriskan. Karena kasus yang mengemuka ke pelataran publik hanya berkisar pada perihal contek-menyontek, kebocoran, kecurangan, jual beli kunci, hingga kontradiksi bangunan wacana sebagian pakar pendidikan yang mempertanyakan efektifitas UN.
Pemberitaan kasus UN tiap tahun tersebut, mengesankan seolah-olah UN dimata siswa adalah momen yang menyeramkan. Terlebih lagi perhelatannya melibatkan berbagai pihak termasuk aktifis yang ikut berkiprah memantau perkembangan lapangan. Bukan hanya itu, tapi politisasi UN pun tak kalah mencolok ketika pejabat berkunjung ke sekolah hanya untuk menggambarkan legitimasi helat UN yang aman terkendali.
Padahal, UN adalah domain keilmuan yang bersifat merdeka dan tak butuh popularitas publik. Dan idealnya yang terlibat cukuplah orang yang berkompeten saja. Sebab terlalu banyaknya kunjungan dari berbagai pihak seperti pejabat dengan alasan inspeksi atau apapun namanya.
Helat UN yang optimal, pihak penyelenggara harus bisa menghadirkan suasana yang kondusif untuk menjaga stabilitas mental anak dalam melakoni proses. Hal ini lebih utama, karena output UN hanya menawarkan dua akibat yaitu lulus atau gagal. Dan hal yang paling menakutkan lagi adalah ketika anak harus menerima kenyataan gagal, tentu guru dan orang tua sebagai orang paling bertanggung jawab dan bekerja ekstra untuk memulihkan kondisi psikis anak.
Dari dua kemungkinan itu, maka wajar kalau guru dan orang tua terkadang harus mengorbankan idealisme dengan menghalalkan segala cara demi sukses anak. Apalagi, UN sudah terlanjur disahkan sebagai satu-satunya instrumen kuantitatif untuk mengukur kualitas anak dalam menatap masa depannya.
Dari titik ini, pemerintah sebaiknya evaluasi dan reposisi kembali makna UN dengan menghadirkan konsep alternatif yang lebih menggambarkan unsur variabelitas kecerdasan anak secara utuh. Sebab jika hanya kepintaran mencontreng menjadi penentu tunggal, maka yang angka tersaji hanyalah gambaran kognisi, sedang potensi bakat, aktualisasi diri, kecerdasan sosial, ketahanan etika dan moralitas dinilai bukan domain yang menentukan. Jika demikian, maka UN hanya bisa meluluskan output kognisi dengan mengabaikan kebermaknaan nilai budaya, kearifan lokal dan pesan keluhuran bangsa.
Padahal bukankah tujuan pendidikan menurut UUD 1945 versi Amendemen terus menggiring output pendidikan untuk beriman, bertakwa, dan berahlak dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Jika semangat UU dibenturkan dengan realitas, sepertinya UN bukanlah instrumen yang menggambaran kualitas anak secara utuh.
Wallahu a’lam bissawaab
Penulis adalah Pemerhati Sosial, Staf Pengajar IAIN STS Jambi