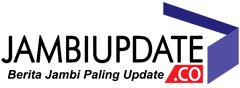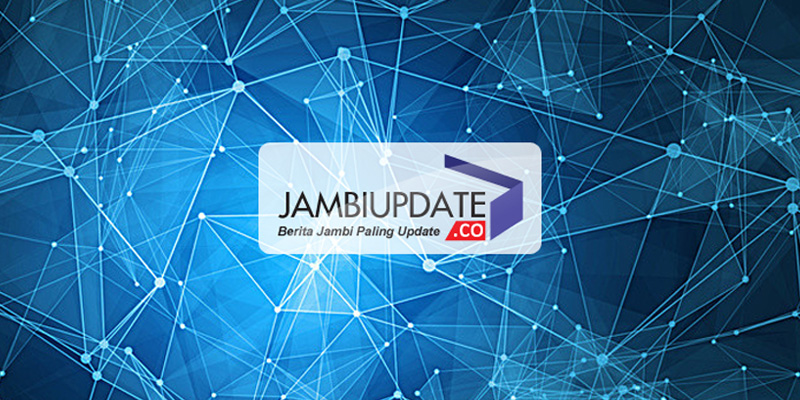Tahun 2013 benar-benar menjadi tahun politik. Betapa tidak, menjelang pelaksanaan pemilu keempat pasca reformasi di tahun 2014, panggung politik kita disuguhi beragam akrobat politik. Sebut saja misalnya, fenomena politisi kutu loncat hingga rekruitmen pesohor menjadi calon legislatif untuk dijadikan vote getter bagi parpol. Pemilu yang diharapkan menjadi titik tolak berjalannya demokrasi di negeri ini, tidak kunjung terwujud sesuai harapan publik. Euforia berdemokrasi pasca terbelenggu rezim otoriter selama puluhan tahun nyatanya hanya dinikmati oleh segelintir elit politik.
Wacana pengkerdilan jumlah partai hingga perdebatan sistem pemilu yang akan dipakai, misalnya, menunjukkan bagaimana tarik ulur elit politik di parlemen mewujudkan kepentingan partainya. Meski perdebatan tersebut telah usai yang ditandai dengan lahirnya UU no 8 tahun 2012 tentang Pemilu dan UU no 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, namun revisi aturan main dalam demokrasi tetap diperlukan untuk menopang keberlanjutan demokrasi. Jumlah peserta partai politik di 2014 nanti yang jauh lebih kecil dari pemilu 2009, bisa menjadi langkah awal untuk mendesain sistem pemilu yang berorientasi pada efektifitas pemerintahan.
Namun sayangnya, dari sekian banyak isu yang diperdebatkan, partisipasi politik menjadi isu yang dianggap tidak “seksi” untuk dikupas. Padahal partisipasi politik seperti yang dijelaskan Liddle dkk dalam bukunya yang berjudul Kuasa Rakyat (2012), merupakan inti dari demokrasi. Terlepas dari perdebatan teoritisi demokrasi elitis dan teoritisi demokrasi liberal klasik tentang partisipasi politik dalam pemilu, yang perlu kita tegaskan adalah bahwa keterlibatan warga negara dalam arena politik ialah bagian penting dari demokrasi itu sendiri. Partisipasi warga menjadi penting karena demokrasi sejatinya dimaknai sebagai konsep “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”.
Lalu, bagaimana dengan kondisi partisipasi di negara kita? Mengapa isu ini tidak menjadi bagian dari pembahasan dalam pembuatan aturan main Pemilu. Berdasarkan data Lembaga Survey Indonesia, semenjak Pemilu dilaksanakan pertama kali di Indonesia hingga Pemilu 2009 yang lalu, tingkat partisipasi politik masyarakat di Indonesia memang masih di atas rata-rata partisipasi politik dunia yang berada pada kisaran 64%. Data LSI menunjukkan bahwa pada Pemilu 1955 tingkat partisipasi politik di Indonesia sekitar 87%, Pemilu 1999 naik menjadi 93,3 %, lalu Pemilu 2004 turun menjadi 84, 9% sedangkan pada Pemilu 2009 yang lalu kembali mengalami penurunan hingga berada pada kisaran angka 70, 99%. Sementara Pemilu yang berlangsung pada masa Orde Baru tidak dijadikan salah satu tolak ukur, karena partisipasi politik masyarakat pada masa itu berbasis pada demokrasi semu yang diciptakan rezim otoritarian.
Sekalipun tingkat partisipasi bukanlah satu-satunya tolak ukur dalam Pemilu, namun penurunan angka partisipasi ini perlu menjadi perhatian para pejuang demokrasi negeri ini. Belum lagi pengalaman mutakhir di beberapa Pemilukada yang menunjukkan bahwa partisipasi pemilih semakin menurun. Sekedar menyebut contoh, partisipasi pemilih di Pemilukada Jawa Barat hanya menyentuh angka 63,85 % dari total pemilih. Terakhir, Pemilukada Sumatera Utara yang hanya diikuti kurang dari 50% jumlah pemilih. Apakah kondisi ini mengindikasikan bahwa masyarakat kita telah jenuh dengan ritus demokrasi yang sedang berjalan. Tentu kita tidak ingin masyarakat menjadi teralienasi dengan adanya penyelenggaraan Pemilu yang sudah dianggap sangat demokratis ini.
Poin pentingnya memang bukan pada angka partisipasinya, melainkan esensi dari alasan masyarakat ikut serta dalam Pemilu. Hanya saja, partisipasi politik kita akan jauh terus menurun di bawah angka 50% jika tidak dikawal. Pentingnya merawat keikutsertaan masyarakat dalam Pemilu karena terkait erat dengan legitimasi. Rendahnya partisipasi warga di satu sisi bisa dibaca sebagai lemahnya dukungan terhadap kandidat terpilih. Meski di sisi lain, kualitas demokrasi tidak sepenuhnya hanya diukur dari tingkat partisipasi.
Untuk itu, peluang untuk memperbaiki kualitas partisipasi politik masyarakat kita masih terbuka. Beragam alasan masyarakat untuk tidak memilih dalam Pemilu seperti; tidak percaya akan adanya efek setelah Pemilu, serta tidak percaya kepada partai dan kandidat, perlu dicermati secara serius. Sementara alasan teknis seperti tidak terdaftar, tidak di rumah, sakit dan tidak tahu, menjadi tugas penting KPU untuk mencari solusinya. Dengan demikian, persoalan partisipasi tidak boleh diabaikan jika kita masih memilih demokrasi sebagai instrumen untuk meraih kesejahteraan.
(Penulis adalah mahasiswa asal Jambi, sedang menempuh pendidikan Pascasarjana Politik dan Pemerintahan, FISIPOL UGM)
Wacana pengkerdilan jumlah partai hingga perdebatan sistem pemilu yang akan dipakai, misalnya, menunjukkan bagaimana tarik ulur elit politik di parlemen mewujudkan kepentingan partainya. Meski perdebatan tersebut telah usai yang ditandai dengan lahirnya UU no 8 tahun 2012 tentang Pemilu dan UU no 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, namun revisi aturan main dalam demokrasi tetap diperlukan untuk menopang keberlanjutan demokrasi. Jumlah peserta partai politik di 2014 nanti yang jauh lebih kecil dari pemilu 2009, bisa menjadi langkah awal untuk mendesain sistem pemilu yang berorientasi pada efektifitas pemerintahan.
Namun sayangnya, dari sekian banyak isu yang diperdebatkan, partisipasi politik menjadi isu yang dianggap tidak “seksi” untuk dikupas. Padahal partisipasi politik seperti yang dijelaskan Liddle dkk dalam bukunya yang berjudul Kuasa Rakyat (2012), merupakan inti dari demokrasi. Terlepas dari perdebatan teoritisi demokrasi elitis dan teoritisi demokrasi liberal klasik tentang partisipasi politik dalam pemilu, yang perlu kita tegaskan adalah bahwa keterlibatan warga negara dalam arena politik ialah bagian penting dari demokrasi itu sendiri. Partisipasi warga menjadi penting karena demokrasi sejatinya dimaknai sebagai konsep “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”.
Lalu, bagaimana dengan kondisi partisipasi di negara kita? Mengapa isu ini tidak menjadi bagian dari pembahasan dalam pembuatan aturan main Pemilu. Berdasarkan data Lembaga Survey Indonesia, semenjak Pemilu dilaksanakan pertama kali di Indonesia hingga Pemilu 2009 yang lalu, tingkat partisipasi politik masyarakat di Indonesia memang masih di atas rata-rata partisipasi politik dunia yang berada pada kisaran 64%. Data LSI menunjukkan bahwa pada Pemilu 1955 tingkat partisipasi politik di Indonesia sekitar 87%, Pemilu 1999 naik menjadi 93,3 %, lalu Pemilu 2004 turun menjadi 84, 9% sedangkan pada Pemilu 2009 yang lalu kembali mengalami penurunan hingga berada pada kisaran angka 70, 99%. Sementara Pemilu yang berlangsung pada masa Orde Baru tidak dijadikan salah satu tolak ukur, karena partisipasi politik masyarakat pada masa itu berbasis pada demokrasi semu yang diciptakan rezim otoritarian.
Sekalipun tingkat partisipasi bukanlah satu-satunya tolak ukur dalam Pemilu, namun penurunan angka partisipasi ini perlu menjadi perhatian para pejuang demokrasi negeri ini. Belum lagi pengalaman mutakhir di beberapa Pemilukada yang menunjukkan bahwa partisipasi pemilih semakin menurun. Sekedar menyebut contoh, partisipasi pemilih di Pemilukada Jawa Barat hanya menyentuh angka 63,85 % dari total pemilih. Terakhir, Pemilukada Sumatera Utara yang hanya diikuti kurang dari 50% jumlah pemilih. Apakah kondisi ini mengindikasikan bahwa masyarakat kita telah jenuh dengan ritus demokrasi yang sedang berjalan. Tentu kita tidak ingin masyarakat menjadi teralienasi dengan adanya penyelenggaraan Pemilu yang sudah dianggap sangat demokratis ini.
Poin pentingnya memang bukan pada angka partisipasinya, melainkan esensi dari alasan masyarakat ikut serta dalam Pemilu. Hanya saja, partisipasi politik kita akan jauh terus menurun di bawah angka 50% jika tidak dikawal. Pentingnya merawat keikutsertaan masyarakat dalam Pemilu karena terkait erat dengan legitimasi. Rendahnya partisipasi warga di satu sisi bisa dibaca sebagai lemahnya dukungan terhadap kandidat terpilih. Meski di sisi lain, kualitas demokrasi tidak sepenuhnya hanya diukur dari tingkat partisipasi.
Untuk itu, peluang untuk memperbaiki kualitas partisipasi politik masyarakat kita masih terbuka. Beragam alasan masyarakat untuk tidak memilih dalam Pemilu seperti; tidak percaya akan adanya efek setelah Pemilu, serta tidak percaya kepada partai dan kandidat, perlu dicermati secara serius. Sementara alasan teknis seperti tidak terdaftar, tidak di rumah, sakit dan tidak tahu, menjadi tugas penting KPU untuk mencari solusinya. Dengan demikian, persoalan partisipasi tidak boleh diabaikan jika kita masih memilih demokrasi sebagai instrumen untuk meraih kesejahteraan.
(Penulis adalah mahasiswa asal Jambi, sedang menempuh pendidikan Pascasarjana Politik dan Pemerintahan, FISIPOL UGM)