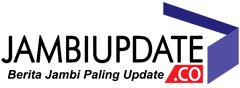JAMBIUPDATE.CO, JAKARTA – Praktik politik uang dianggap paling sulit dihilangkan dalam pesta demokrasi. Ritmenya hanya berpindah. Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) misalnya. Jika sebelumnya yang bermain adalah DPRD, kini beralih ke pimpinan partai politik.
Menkopolhukam Mahfud MD menyebut, politik uang mulai terjadi sejak era Orde Baru. Saat itu, transaksi politik uang berlangsung di DPRD. “Kalau dulu money politic dalam pemilihan kepala daerah itu ada di DPRD. Nah, sekarang berpindah ke pimpinan partai,” kata Mahfud di Jakarta, Senin (24/2).
Dia menyebut di era Orde Baru kekuasaan DPRD dianggap buruk. Karena diberi kekuasaan untuk memilih kepala daerah. Dengan kekuasaan tersebut, sering terjadi praktik money politic untuk memilih kepala daerah. Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menyebut politik uang pernah terjadi di Pilkada Yogyakarta dan Jawa Timur pada era Orde Baru. Pada waktu itu, anggota DPRD diberi uang untuk meloloskan calon kepala daerah.
“Mulai di daerah saya di Yogyakarta. Kepala Daerah mau pemilihan, anggota DPRD-nya 45. Sebanyak 23 orang dikarantina. Dibayar kamu harus pilih ini si A. Jadi kemungkinan kepala daerah terdahulu terjadi jual beli. Itu menjadi bahasan sehari-hari. Kalau begitu kebablasan DPRD yang zaman orde baru,” paparnya.
Menurutnya, transaksi tersebut juga dilakukan secara terang-terangan. Hanya dengan bermodalkan Rp5 miliar, seseorang bisa menjabat sebagai kepala daerah. “Untuk jabatan gubernur misalnya. Waktu itu gampang sekali orang bayar Rp5 miliar satu suara asal memilih gubernur ini. Transaksinya di lobi hotel yang dikontrol oleh ketua fraksi partai,” imbuhnya.
Ia menjelaskan, pemerintah pun mengganti sistem pemilihan kepala daerah yang ada. Melalui UU No 32 Tahun 2004, pemilihan kepala daerah dipilih langsung oleh masyarakat. “Itu terjadi tahun 2004. Karena kemarahan politik terhadap DPRD di berbagai daerah. Sehingga di era-era itu banyak anggota DPRD masuk penjara. Diubahlah UU. DPRD sebagian ditekan gajinya dan diperkecil. Tidak boleh lagi minta laporan pertanggungjawaban. Tapi apakah keadaan lebih baik? Tidak,” ucapnya.
Praktik tersebut kini telah berpindah dari DPRD ke partai politik. “Nggak bayar ke DPRD, bayar ke partai. Mahar namanya. Ini terus terang saja, begitu. Apa betul? Ya betul. Wong sudah dimuat di media begitu. Orang kan bilang tidak ada. Tetapi yang kalah itu melapor. Yang menang tidak,” jelas Mahfud.
Ia meminta di tengah praktik money politic itu, para legislator di daerah bersabar dan mencari solusi pencegahan. “Ketika DPRD diberi kekuasaan menjadi kebablasan, tidak diturunkan lagi. Buruk lagi. Mari kita sekarang mencari keseimbangan baru. Politik itu mencari keseimbangan baru,” bebernya.
Sementara itu, pengamat Politik Ujang Komarudin menyebut jika mahar politik yang dilakukan partai sudah dianggap lazim. Meskipun para petinggi partai mengatakan tidak ada mahar politik, hal ini bukan berarti demikian.
Mahar politik dipastikan ada di setiap pemilihan kepala daerah. Calon kepala daerah harus merogoh kocek tertentu agar bisa mendapat dukungan dari parpol. Besaran biaya tersebut juga bervariatif. Tergantung lobi dan kesepakatan. “Nah parpol ini biasanya tidak mengakui jika ada mahar. Padahal kondisi di lapangan berkata demikian,” ujar Ujang kepada FIN di Jakarta, Senin (24/2).
Dia menilai yang merusak proses pilkada adalah partai politik. Sebab partai memungut mahar politik yang besar. “Coba jika tak ada mahar politik untuk membeli perahu. Lalu kandidat jangan tebar uang. Jika itu dilakukan, maka pilkada langsung tak akan banyak makan biaya,” tutur dosen Universitas Al Azhar ini. (khf/fin/rh)
Sumber: www.fin.co.id