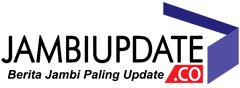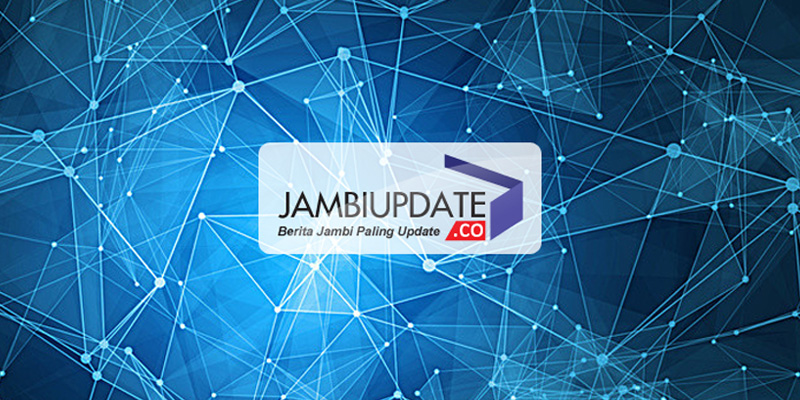Oleh : Asrul Aziz Sigalingging
PENELITIAN demi penelitian telah membuktikan bahwa masyarakat adat merupakan pelindung terbaik hutan tropis dan keanekaragaman hayati di dunia (Madhav Gadghil, et al, 1993). Peran dan kontribusi masyarakat adat dalam menghadapi perubahan iklim sangatlah penting. Bagi masyarakat adat, hutan bukan hanya sebagai sumber pangan dan obat obatan namun juga menjadi identitas sosio - kultural. Melalui praktik pemanfaatan hutan secara arif dan berkelanjutan berdasar tradisi adat istiadat, masyarakat adat memperlihatkan kebiasaannya sebagai pelaku konservasi yang paling efektif yang sangat ahli dalam mengelola, menjaga, bahkan memulihkan hutan yang terdegradasi. Keyakinan dan pengetahuan tradisional inilah yang membantu melestarikan hutan dan keanekaragaman hayati, membuat keseimbangan ekosistem dari generasi ke generasi tetap terjaga hingga memungkinkan kita dan miliaran manusia lainnya dapat terus hidup di bumi ini. Oleh sebab itu harus diakui bila kepastian akses dan pelibatan peran lebih besar masyarakat adat untuk mengelola hutan dan lahan adatnya sesuai tradisi dan budayanya, bukan hanya akan menjadi skenario ketahanan iklim yang hemat biaya seperti yang pernah disinggung oleh Helen Ding, et al (Climate Benefits, Tenure Costs. The Economic Case for Securing Indigenous Land Rights in the Amazon, 2016), namun bahkan menjadi salah satu jaminan terbaik untuk menghadapi perubahan iklim saat ini. Begitu pun halnya seharusnya di tanah air.
Namun, seolah bertolak belakang dengan sains, dalam konteks tanah air, data Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) per agustus 2023 malah mengungkapkan hal sebaliknya. Dari total seluas 26,9 juta hektar luas wilayah adat yang diregistrasi oleh BRWA yang tersebar di 32 provinsi dan 155 kabupaten/kota, hanya sekitar 3,73 juta hektar atau 13,9 % yang sudah ditetapkan pengakuannya oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Masih ada sekitar 23,17 juta hektar wilayah adat yang belum diakui oleh pemerintah daerah. Sedangkan dalam konteks penetapan hutan adat, dari sekitar 20.856.744 hektar luas potensi hutan adat di tanah air hanya seluas 221.648 hektar (123 SK Hutan Adat) yang mendapatkan penetapan oleh pemerintah (BRWA, 09/08/2023). Masih jauh panggang dari api. Bagi sebuah negara kepulauan yang didiami hampir seribu lebih etnis, bahasa, tradisi dan budaya, ini tentu bukan hanya soal angka matematis yang menunjukan disparitas belaka namun lebih sebagai sikap yang membelakangi sains—alih alih sebuah "penghinaan"—untuk sebuah negara yang meletakkan masyarakat adat sebagai identitas nasionalnya dalam konstitusi UUD 1945.
Lemahnya jaminan perlindungan masyarakat adat tentu bukan semata mata persoalan hak atas tanah tetapi juga persoalan mendasar bagi keadilan iklim. Masyarakat adat meski memiliki pengetahuan dan praktik paling baik dalam pengelolaan hutan namun juga adalah pihak paling terdampak perubahan iklim itu sendiri. Maka ambisi iklim di sektor hutan dan tata guna lahan (forest and land use) seharusnya dicapai dengan melibatkan peran seluas luasnya masyarakat adat. Dan politik hukum kebijakan yang menjamin perlindungan masyarakat adat mestinya adalah fondasi bagi kebijakan iklim nasional. Kontradiksi keduanya (baca : politik hukum pengakuan masyarakat adat dan kebijakan iklim) bukan saja akan melanggenggkan pelanggaran hak hak masyarakat adat namun juga menjadi inti dari krisis iklim itu sendiri. Lantas, apa penyebab persoalan ini ?
Batu Sandungan
Jika ditarik mundur satu dekade lebih lalu penyebab kesenjangan ini sejatinya berakar dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 35/2012 yang masih mempertahankan norma pengakuan bersyarat bagi Masyarakat Hukum Adat (MHA). Ketentuan ini secara ekplisit menyatakan bahwa penetapan hutan adat harus diawali terlebih dahulu dengan pengukuhan keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum melalui Peraturan Daerah (Perda) yang diterbitkan Pemerintah Daerah (Pemda). Perda menjadi dasar bagi KLHK untuk menetapkan hutan adat. Sehingga memang penetapan hutan adat oleh KLHK sangat bergantung dengan adanya Perda. Satu sisi memang putusan MK 35/2012 telah mengeluarkan hutan adat dari hutan negara, namun dalam beslissing yang sama, MK berkukuh mempertahankan pengakuan bersyarat di dalam Pasal 67 UU Kehutanan yang menjadi bagian objek gugatan. Maksud MK mempertahankan pengaturan tentang pengakuan bersyarat ini kesannya memang ditujukan agar putusan MK yang mengeluarkan hutan adat dari hutan negara dapat “dieksekusi” dalam kerangka otonomi daerah. Dengan pertimbangan semacam ini, MK berpandangan bahwa mekanisme desentralisasi sepenuhnya akan bekerja responsif untuk mengidentifikasi, memverfikasi dan mevalidasi eksistensi masyarakat adat di daerahnya masing masing untuk diakui dan dilindungi melalui Perda.
Kalkulasi MK ternyata meleset. Gagasan untuk menegakan pengakuan dan perlindungan MHA dalam kerangka otonomi daerah melalui skema Perda ternyata membutuhkan ongkos legislasi yang tidak kecil. Catatan pribadi penulis, untuk mendorong terbitnya satu Perda realitanya bahkan bisa mencapai 80 juta rupiah bahkan lebih dan angkanya bisa berbeda-beda di tiap daerah sesuai kebutuhan dan tingkatan pemerintahannya. Selain faktor biaya, cenderung pasifnya Pemda dalam mewujudkan amanat Putusan MK 35/2012 juga satu persoalan yang tidak bisa dinafikan sampai saat ini. Kendala political will yang rendah ini akhirnya menuntut masyarakat adat harus menjadi pelobi yang cakap, yang kadang kadang harus berhadapan dengan intrik politik elektoral karena prosedur dan kewenangan pengakuan sebagai subjek hukum ini sudah dikomodifikasi pula semacam komoditas politik yang dipertaruhkan plus diperebutkan dalam palagan elektoral daerah seperti Pilkada.
Tidak jarang bila upaya untuk mendapatkan sebuah Perda justru sangat bergantung pada momentum politik yang electoral minded bukan karena dorongan untuk menegakkan perintah amanah konsitusi. Alhasil, maksud MK semula agar pengakuan bersyarat masyarakat hukum adat “dieksekusi” dalam kerangka otonomi daerah realitanya malah menghadapkan—alih alih “menjerumuskan” masyarakat adat dalam resiko politik transaksional. Padahal, jika daerah benar-benar pure ingin mengoperasionalkan putusan MK 35/2012, sejak putusan ini terbit Pemda sebetulnya dapat saja “jemput bola” memasukan pembentukan kebijakan pengakuan dan perlindungan MHA itu sendiri dalam kebijakan agenda pembangunan daerahnya masing-masing baik dalam RPJMD maupun RKP daerahnya. Namun sayangnya sama sekali nihil.
Ini terjadi memang bukan karena otonomi daerah tidak relevan dalam konteks pengakuan masyarakat adat namun lebih pada persoalan ketidaksinkronan regulasi, tumpang tindih kewenangan, biaya, ego sektoral, prioritas daerah yang berbeda-beda, yang bersilang tempat dengan minimnya kapasitas dan pemahaman daerah sehingga political will tadi lebih merupakan buah simalakama dari kerangka pengakuan bersyarat yang tidak diturunkan dalam satu mekanisme undang undang yang terintegrasi dan efisien yang bisa menjadi rujukan bagi semua daerah dan oleh masyarakat adat itu sendiri. Tak heran bila meski setelah satu dekade lebih putusan MK 35/2012, kerangka pengakuan bersyarat ini tetap relevan untuk dikritisi hingga saat ini.
Apa logikanya untuk diakui sebagai subjek hukum, masyarakat adat yang notabene adalah identitas nasional harus menjalani prosedur yang kompleks penuh lika liku ketidakpastian sebagai syarat untuk mendapatkan akses hutan adatnya yang secara faktual dan etno-historis adalah tanah mereka ? Dengan alat ukur yang sama bandingkan dengan perusahaan yang hanya membutuhkan syarat administratif untuk diakui sebagai subjek hukum demi mendapatkan hak penguasaan hutan ratusan ribu hektar sekalipun para pemilik korporasi ini kita tak tahu dimana rimbanya. Dari persfektif ekonomi politik, disparitas ini dengan sendirinya mengonfirmasi konflik dan ketimpangan penguasaan sumber daya alam yang tidak adil selama ini. Hampir 94,8 persen atau sekitar 53 juta hektare penguasaan lahan berada di tangan korporasi sementara penguasaan yang berada di tangan rakyat hanya 2,7 juta hektare (Walhi, Agustus 2022). Sebagian besar penguasaan sumber daya alam yang dikuasai perusahaan-perusahaan besar ini juga terdapat di wilayah adat masyarakat adat yang menyebabkan konflik berkepanjangan sampai saat ini.
Akses Keadilan
Maka untuk mengakhiri polemik dan status quo ini sudah selayaknya pemerintah mengambil langkah diskresi agar masyarakat adat memperoleh keadilan atas hak-haknya. Pengakuan sebagai subjek hukum haruslah diletakkan dalam kerangka akses keadilan (acces to justice) dalam hal ini akses keadilan bagi masyarakat adat untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam pengelolaan sumber daya alam. Akses keadilan merupakan prinsip dasar dalam negara hukum (rule of law). Jhon Rawls menyebutkan, keadilan adalah kesetaraan (justice is fairness). Dalam keadilan, distribusi yang adil atas semua kesempatan, kedudukan, peranan serta manfaat-manfaat atau nilai-nilai sosial yang terdapat di dalam masyarakat merupakan keharusan (Jhon Rawls, 1971). Sedangkan dalam negara hukum, untuk menciptakan proses hukum yang adil (due process of law), asas persamaan dihadapan hukum (equality before the law) harus diwujudkan melalui pembentukan hukum yang menjamin persamaan hak (legislations to ensure equality of rights). Tanpanya mustahil mencapai keadilan itu sendiri (a nonsense justice).
Dalam paradigma politik hukum (law and policy making), kebijakan pengakuan dan perlindungan terhada MHA sudah mestinya dilihat dan diletakkan dalam lensa hukum responsif. Sebagaimana yang ditekankan Nonet dan Selznick, hukum mestinya menawarkan sesuatu yang lebih daripada sekedar keadilan prosedural, tetapi juga harus mampu berfungsi sebagai fasilitator dari respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial yang berkembang (Philippe Nonet & Philip Selznick, 2003). Hukum adalah instrumen untuk melayani kebutuhan manusia, bukan sebaliknya. Dalam makna ini, isolasi sistem hukum dari berbagai institusi sosial di sekitarnya justru berdampak buruk dari sisi kebutuhan manusia itu sendiri. Untuk itu hukum harus keluar dari jebakan formalisme yang kaku, dan harus mampu mengakomodasi perubahan-perubahan sosial demi tercapainya keadilan dan emansipasi publik. Dalam arena legislasi, pikiran ini juga harus tercermin dalam diri para legislator.