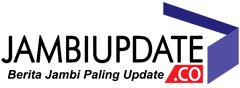“Cinta terlahir di dunia ini dari sebutir apel, lalu terlahir kembali dari sekeranjang mangga.”
Dedaunan kering itu ditumpuk begitu saja di sudut halaman belakang. Dua kali sehari Ikhsan akan membakarnya. Semenjak pohon mangga tetangganya tumbuh membesar, pekerjaan Ikhsan semakin berat. Menyapu halaman menjadi pekerjaan tersulit sekaligus dibencinya. Tersulit karena guguran daunnya semakin banyak, dibenci karena pohon itu tumbuh bukan di halaman belakang rumahnya.
Dulu Ayahnya sering meminta penghuni rumah sebelah untuk rajin memangkas cabang-cabang yang menyeruak ke halaman belakang rumah mereka. Tapi semenjak tetangganya itu pindah ke lain kota, tidak ada lagi kegiatan pangkas-memangkas itu. Sudah enam bulan rumah itu kosong. Selama itu pula Ikhsan dan Ayahnya terpaksa melakukan pemangkasan sendiri sebulan sekali.
Pohon mangga itu tumbuh tidak terlalu jauh dari pagar yang membatasi halaman belakang. Semakin tumbuh besar, cabang-cabangnya seolah sengaja meloncati pagar tembok setinggi dua meter. Pohon itu subur dan rimbun. Akibatnya, halaman belakang rumah Ikhsan menjadi tempat guguran daun yang bebas tanpa permisi.
Sejak dua tahun lalu, pohon itu mulai berbuah. Jenisnya, mangga kuini. Buahnya lebat hingga ke ujung-ujung ranting. Setelah guguran daun, pekerjaan lain adalah memunguti buah yang jatuh membusuk.
“Busetttt, sudah tertimpa daung kering, sekarang mangga busuk pula,” gerutu Ikhsan ketika menyapu setiap sore. Keringatnya selalu serimbun dedaunan pohon itu.
Dulu tetangganya selalu mengikhlaskan mangga yang berbuah di ranting yang menjuntai ke halaman rumah Ikhsan.
“Males banget, siapa juga yang mau metik. Mending metik di pasar, nggak pake perjuangan congkel sana-sini,” protes Ikhsan.
Sering pula tetangganya mengirim sekeranjang mangga yang mereka petik sendiri di halamannya. Mungkin protes Ikhsan terdengar hingga ke kuping mereka.
“Segini banyak emangnya kita mau mandi jus mangga, apa?”
Ada-ada saja protes Ikhsan saking kesalnya. Kata Ayahnya, bibit pohon mangga itu dibawa langsung oleh nenek si empunya rumah. Makanya pohon itu tidak boleh ditebang demi menjaga wasiat.
“Wasiat kok pohon mangga? Coba pohon duit, pasti cabangnya penuh cangkokan!”
“Hushh!”
Ikhsan dan Ayahnya terkekeh.
***
Sore yang lain, seperti biasa Ikhsan melaksanakan tugasnya. Menyapu. Lagi-lagi menyebalkan tapi tugas mulia itu sudah kadung menjadi tanggung jawabnya. Lebih tepatnya lagi, nasibnya. Pernah dia mengusulkan untuk menyewa tukang kebun saja khusus untuk menyapu.
“Usulnya brilian juga. Bayarnya pake uang jajan kamu, ya,” goda Ayahnya enteng.
“Ayah nggak asyik, ah!”
“Sudahlah, hitung-hitung kamu olah raga. Anggap aja pemanasan sebelum kamu latihan karate nanti malam.”
“Astaga Ayah, pinggang Ikhsan udah keburu cedera kalau tiap hari masih begini. Cedera karena karate, kek. Mana keren cedera karena nyapu?”
Jadinya sore itu Ikhsan tetap harus menjalankan kewajibannya. Sesekali dia menyapu bersama Ayahnya. Tetapi lebih sering hanya ditemani sapu lidi yang setia mendengar omelannya. Cuma dialah satu-satunya harapan keluarga demi kebersihan dan keindahan halaman belakang.
Bang Diar sudah bebas tugas karena kuliah di lain kota. Rasanya dia ingin cepat-cepat menyusul abangnya itu. Tapi sekarang dia masih di kelas dua SMA. Masih ada setahun lagi sebelum misi penyelamatan diri terlaksanakan. Berarti setahun lagi kencan sore bersama sapu lidi. Huh!
Sedang asyik-asyiknya melamun sambil menyapu. Tiba-tiba telinga Ikhsan mendengar suara sapu lidi dari halaman sebelah. Halaman tempat pohon mangga wasiat itu bertakhta. Seseorang sedang menyapu. Dia teringat cerita ibunya tadi pagi, rumah sebelah sudah ada penghuni baru. Rumah itu akhirnya dijual dan sudah laku sejak bulan lalu.
“Halo, halo, siapa yang nyapu di situ?”
Ikhsan berhenti menyapu dan berteriak ke arah pagar. Beberapa saat dia menunggu tapi tidak ada balasan. Dia mengulang sekali lagi.
“Halo, halo, siapa yang lagi nyapu?”
Belum terdengar juga balasannya.
“Halo, halo, tetangga baru, ya?”
Suara sapu lidi dari seberang tembok kemudian berhenti.
“Ada apa sih nanya-nanya?”
Ikhsan tersenyum, akhirnya ada balasan juga. Tapi, eh, kok suara cewek? Dari suaranya kedengarannya masih muda.
“Ya, nanya aja. Tetangga baru, ya? Kirain sapunya nyapu sendiri.”
“Emangnya sapu nenek sihir?”
Ikhsan ngakak.
“Kamu nyapu sendiri?”
“Enggak, berdua.”
“Hah, sama siapa?”
“Ya, sama sapulah. Udah ah!”
Eh, ini cewek tengil juga, pikir Ikhsan.
“Emang enak nyapu daun-daun mangga yang numpuk?”
Ikhsan iseng menggoda dengan nada mengejek. Suara sapu di seberang pagar seketika seperti menyapu asal-asalan dengan terburu-buru. Lalu suaranya berhenti. Godaan Ikhsan tidak berbalas lagi. Tapi di hari-hari berikutnya, dia terus menggoda.
***
Dini dan keluarganya menempati rumah barunya. Rumah itu besar dengan halaman belakang yang luas dan sejuk. Rumah itu benar-benar cocok sesuai keinginan Ayahnya yang seorang pelukis. Ayahnya butuh ruang luas untuk studionya. Sementara itu halaman belakangnya sangat cocok untuk tempat Ayahnya menyelesaikan lukisannya.
Dini juga menyukai rumah itu. Tapi tidak dengan halaman belakangnya. Pohon mangga yang besar dan rimbun di situ membuat ia jengkel. Daunnya bertebaran kemana-mana. Jika angin sedikit kencang, daunnya banyak berjatuhan, berserakan ke mana-mana, hingga terbang meloncati jendela dapur. Sudah begini, Dini juga yang harus turun tangan.
Menurut Ayahnya, sangat sulit mencari tukang kebun. Ayahnya meminta berkali-kali agar Dini yang menyapu sementara waktu. Dini sudah protes walau tugasnya hanya dua hari sekali.
Dedaunan kering itu ditumpuk begitu saja di sudut halaman belakang. Dua kali sehari Ikhsan akan membakarnya. Semenjak pohon mangga tetangganya tumbuh membesar, pekerjaan Ikhsan semakin berat. Menyapu halaman menjadi pekerjaan tersulit sekaligus dibencinya. Tersulit karena guguran daunnya semakin banyak, dibenci karena pohon itu tumbuh bukan di halaman belakang rumahnya.
Dulu Ayahnya sering meminta penghuni rumah sebelah untuk rajin memangkas cabang-cabang yang menyeruak ke halaman belakang rumah mereka. Tapi semenjak tetangganya itu pindah ke lain kota, tidak ada lagi kegiatan pangkas-memangkas itu. Sudah enam bulan rumah itu kosong. Selama itu pula Ikhsan dan Ayahnya terpaksa melakukan pemangkasan sendiri sebulan sekali.
Pohon mangga itu tumbuh tidak terlalu jauh dari pagar yang membatasi halaman belakang. Semakin tumbuh besar, cabang-cabangnya seolah sengaja meloncati pagar tembok setinggi dua meter. Pohon itu subur dan rimbun. Akibatnya, halaman belakang rumah Ikhsan menjadi tempat guguran daun yang bebas tanpa permisi.
Sejak dua tahun lalu, pohon itu mulai berbuah. Jenisnya, mangga kuini. Buahnya lebat hingga ke ujung-ujung ranting. Setelah guguran daun, pekerjaan lain adalah memunguti buah yang jatuh membusuk.
“Busetttt, sudah tertimpa daung kering, sekarang mangga busuk pula,” gerutu Ikhsan ketika menyapu setiap sore. Keringatnya selalu serimbun dedaunan pohon itu.
Dulu tetangganya selalu mengikhlaskan mangga yang berbuah di ranting yang menjuntai ke halaman rumah Ikhsan.
“Males banget, siapa juga yang mau metik. Mending metik di pasar, nggak pake perjuangan congkel sana-sini,” protes Ikhsan.
Sering pula tetangganya mengirim sekeranjang mangga yang mereka petik sendiri di halamannya. Mungkin protes Ikhsan terdengar hingga ke kuping mereka.
“Segini banyak emangnya kita mau mandi jus mangga, apa?”
Ada-ada saja protes Ikhsan saking kesalnya. Kata Ayahnya, bibit pohon mangga itu dibawa langsung oleh nenek si empunya rumah. Makanya pohon itu tidak boleh ditebang demi menjaga wasiat.
“Wasiat kok pohon mangga? Coba pohon duit, pasti cabangnya penuh cangkokan!”
“Hushh!”
Ikhsan dan Ayahnya terkekeh.
***
Sore yang lain, seperti biasa Ikhsan melaksanakan tugasnya. Menyapu. Lagi-lagi menyebalkan tapi tugas mulia itu sudah kadung menjadi tanggung jawabnya. Lebih tepatnya lagi, nasibnya. Pernah dia mengusulkan untuk menyewa tukang kebun saja khusus untuk menyapu.
“Usulnya brilian juga. Bayarnya pake uang jajan kamu, ya,” goda Ayahnya enteng.
“Ayah nggak asyik, ah!”
“Sudahlah, hitung-hitung kamu olah raga. Anggap aja pemanasan sebelum kamu latihan karate nanti malam.”
“Astaga Ayah, pinggang Ikhsan udah keburu cedera kalau tiap hari masih begini. Cedera karena karate, kek. Mana keren cedera karena nyapu?”
Jadinya sore itu Ikhsan tetap harus menjalankan kewajibannya. Sesekali dia menyapu bersama Ayahnya. Tetapi lebih sering hanya ditemani sapu lidi yang setia mendengar omelannya. Cuma dialah satu-satunya harapan keluarga demi kebersihan dan keindahan halaman belakang.
Bang Diar sudah bebas tugas karena kuliah di lain kota. Rasanya dia ingin cepat-cepat menyusul abangnya itu. Tapi sekarang dia masih di kelas dua SMA. Masih ada setahun lagi sebelum misi penyelamatan diri terlaksanakan. Berarti setahun lagi kencan sore bersama sapu lidi. Huh!
Sedang asyik-asyiknya melamun sambil menyapu. Tiba-tiba telinga Ikhsan mendengar suara sapu lidi dari halaman sebelah. Halaman tempat pohon mangga wasiat itu bertakhta. Seseorang sedang menyapu. Dia teringat cerita ibunya tadi pagi, rumah sebelah sudah ada penghuni baru. Rumah itu akhirnya dijual dan sudah laku sejak bulan lalu.
“Halo, halo, siapa yang nyapu di situ?”
Ikhsan berhenti menyapu dan berteriak ke arah pagar. Beberapa saat dia menunggu tapi tidak ada balasan. Dia mengulang sekali lagi.
“Halo, halo, siapa yang lagi nyapu?”
Belum terdengar juga balasannya.
“Halo, halo, tetangga baru, ya?”
Suara sapu lidi dari seberang tembok kemudian berhenti.
“Ada apa sih nanya-nanya?”
Ikhsan tersenyum, akhirnya ada balasan juga. Tapi, eh, kok suara cewek? Dari suaranya kedengarannya masih muda.
“Ya, nanya aja. Tetangga baru, ya? Kirain sapunya nyapu sendiri.”
“Emangnya sapu nenek sihir?”
Ikhsan ngakak.
“Kamu nyapu sendiri?”
“Enggak, berdua.”
“Hah, sama siapa?”
“Ya, sama sapulah. Udah ah!”
Eh, ini cewek tengil juga, pikir Ikhsan.
“Emang enak nyapu daun-daun mangga yang numpuk?”
Ikhsan iseng menggoda dengan nada mengejek. Suara sapu di seberang pagar seketika seperti menyapu asal-asalan dengan terburu-buru. Lalu suaranya berhenti. Godaan Ikhsan tidak berbalas lagi. Tapi di hari-hari berikutnya, dia terus menggoda.
***
Dini dan keluarganya menempati rumah barunya. Rumah itu besar dengan halaman belakang yang luas dan sejuk. Rumah itu benar-benar cocok sesuai keinginan Ayahnya yang seorang pelukis. Ayahnya butuh ruang luas untuk studionya. Sementara itu halaman belakangnya sangat cocok untuk tempat Ayahnya menyelesaikan lukisannya.
Dini juga menyukai rumah itu. Tapi tidak dengan halaman belakangnya. Pohon mangga yang besar dan rimbun di situ membuat ia jengkel. Daunnya bertebaran kemana-mana. Jika angin sedikit kencang, daunnya banyak berjatuhan, berserakan ke mana-mana, hingga terbang meloncati jendela dapur. Sudah begini, Dini juga yang harus turun tangan.
Menurut Ayahnya, sangat sulit mencari tukang kebun. Ayahnya meminta berkali-kali agar Dini yang menyapu sementara waktu. Dini sudah protes walau tugasnya hanya dua hari sekali.
“Ayah, ayolah cepat cari. Dini nggak kuat nyapu terus. Halamannya terlalu heboh. Dan pohon mangga itu daunnya lebay banget. Jatuhnya kayak musim gugur datang tiap menit.”
“Lho, di sini ada musim gugur? Ntar lagi ada musim salju, dong.”
Ayahnya tertawa kecil.
“Dini serius, nih.”
Wajahnya merengut merasa tidak diperhatikan. Ayahnya terlalu serius membetulkan letak lukisan di studio.
“Tukang kebun di sebelah itu genit. Godain Dini terus kalo lagi nyapu. Sebel!”
“Nah, kamu bisa sekalian tanya, siapa tahu ada temennya yang mau kerja di sini. Syukur-syukur dia mau kerja juga di sini. Coba kamu tanyain.”
“Amit-amit! Genit gitu kerja di sini?”
“Genit gimana? Ya, kamu coba tanyain. Siapa tahu dia bisa bantu.”
Dini makin merengut. Ayahnya makin tenggelam memerhatikan lukisan. Sementara itu, sore menjelang. Kali ini giliran dia yang harus menyapu.
“Ciee, masih nyapu juga? Mana katanya ada tukang kebun?”
Dini manyun dan terus menyapu. Dia malas menggubris suara dari pagar tembok sebelah itu. Semakin digubris malah semakin jadi digoda terus.
“Eh, jangan-jangan, aku lagi ngomong sama tukang kebunnya, nih..”
Suara di balik tembok itu tertawa mengejek. Dini akhirnya kesal dan bersuara juga.
“Sembarangan! Kamu tuh yang tukang kebun.”
“Lho, kok balik nuduh?”
“Nggak ngaku juga nggak apa-apa. Eh, ada lagi nggak tukang kebun kayak kamu? Mau dong kerja di sini. Atau kamu juga boleh rangkap kerja di sini.”
Giliran Dini kali ini yang iseng menggoda.
Mereka masih saling meledek sambil terus menyapu.
“Enak aja. Aku yang punya rumah ini tauk. Kerja rodi gini juga gara-gara pohon manggamu yang rese ini!”
Pecah tawa Dini seketika.
“Hahaha.. Oh jadi kamu terpaksa nyapu karena pohon mangga ini? Emang enak??”
Dan ledek-meledek itu berlangsung terus selama sebulan. Ayah Dini masih juga belum mendapatkan tukang kebun. Sementara itu, pohon mangga itu sudah berbuah lagi. Saking suburnya, setahun bisa berbunga dua kali dan tumbuhlah buah-buah mangga.
Buahnya yang melimpah seakan tidak akan habis dimakan sendiri tiap hari. Ayah Dini berniat membagi dengan tetangga sekitar sekaligus sebagai tanda perkenalan. Dan pekerjaan antar-mengantar buah itu tak lain menjadi tugasnya Dini.
Sampailah Dini di depan pintu rumah Ikhsan dengan sekeranjang mangga. Kebetulan Ikhsan yang membukakan pintu. Setelah basa-basi berkenalan sebentar, niat usil Ikhsan muncul karena mengenali suara Dini.
“Oh ya, salam buat nenek sihir yang suka nyapu sore-sore itu, ya.”
Wajah Dini seketika memerah kesal. Dia tahu cowok di depannya sedang usil. Dia juga mengenali suara Ikhsan.
“Oh, iya dia pernah cerita kalau udah kenalan sama tukang kebun kegatelan di rumah ini. Nggak nyangka banget itu kamu!”
Kali ini wajah Ikhsan yang geram. Dini segera melangkah keluar hingga Ikhsan jadi teringat sesuatu.
“Eitts, tunggu. Kamu anak baru di SMA Pertiwi, ya?”
Dini menghentikan langkah, menoleh ke arah Ikhsan.
“Kok tahu?
“Aku kan sekolah di situ. Ya, jadi tahu. Nanti kamu juga lama-lama bakal tahu siapa aku.”
“Duh, ngapain nunggu lama-lama? Sekarang aja udah tahu. Kamu itu tetangga, merangkap teman satu sekolah, merangkap tukang kebun juga di rumah ini. Wekkk!”
Dini segera berlari pulang.
Ikhsan mematung di depan pintu dengan sekeranjang mangga.
***
Dini dan Ikhsan akhirnya saling kenal juga dengan tak sengaja. Pertemuan di pintu rumah Ikhsan itu membekas di hati masing-masing. Siapa yang menyangka kalau mereka satu sekolah walau berbeda kelas.
Ikhsan dengan bangga bercerita ke teman-temannya kalau si Dini Puspitasari, ternyata adalah tetangga barunya. Dini, anak baru di sekolah mereka, memang langsung jadi primadona sejak hari pertama bersekolah di SMA Pertiwi. Maklum, selain cantik, tersiar kabar dia putri seorang maestro lukis yang sangat terkenal hingga ke mancanegara.
Menurut kabar yang lain pula, dia anak yang cerdas sewaktu SMP. Sewaktu kelas tiga, dia pernah mewakili sekolahnya di Olimpiade Matematika tingkat Nasional. Sayang saja kabar-kabar ini berembus dengan kabar lain yang tidak mengenakkan. Sejak hari pertama, Dini dikenal jutek dan tidak mau berbaur dengan teman satu kelasnya. Ikhsan tak kalah menambahi kalau di rumah pun Dini juga memang jutek.
Hampir sebulan di SMA Pertiwi, Dini jadi tahu siapa dia seorang Ikhsan Arifin. Cowok tetangganya itu ternyata punya segudang prestasi di bidang karate. Semua siswa dari kelas satu sampai kelas tiga mengenali Ikhsan. Tidak perlu survei siapa cowok yang paling sering gentayangan di pikiran cewek-cewek anak SMA Pertiwi. Pasti nama Ikhsan Arifin yang paling merajai lembar survei.
Hubungan Dini dan Ikhsan mirip kucing dan anjing yang susah akur walau dengan campur tangan PBB sekalipun. Di sekolah, mereka saling cuek seolah-olah tidak kenal. Situasi ini membuat Ikhsan menjadi bulan-bulanan temannya.
“Katanya kalian tetanggaan, kok nggak ngobrol? Ajakin berangkat dan pulang bareng kek sekalian pedekate.”
“Kalo kelamaan, jangan menyesal diserobot anak kelas tiga.”
“Jangan-jangan kalian pura-pura, di rumah malah mesra. Diam-diam udah jadian. Idih, basi banget permainannya.”
Mesra? Jadian? Di rumah pun Ikhsan dan Dini makin semrawut hubungannya. Apa lagi setiap episode menyapu halaman.
“Hei, pohon mangga ini ditebang aja. Daunnya makin godrong, tuh!”
“Tebang aja pake gigimu yang gondrong.”
“Huh, omongannya nggak penting banget.”
Ledek-meledek seakan tidak pernah selesai. Pohon mangga menjadi saksi perseteruan Ikhsan dan Dini.
***
Rasa benci bisa jadi malah berbalik suka. Setelah suka terbitlah gengsi. Sebenarnya situasi ini gampang banget dijumpai di film atau di novel. Tapi ternyata ada juga di kehidupan nyata. Buktinya ada pada Ikhsan dan Dini. Dari saling meledek, berkembang jadi saling memikirkan. Diam-diam mulai saling memerhatikan di sekolah, lalu saling menunggu sore di bawah pohon mangga. Dramanya mulai berganti skenario.
Pohon mangga yang buahnya terus-terusan beranak menjadi korban perubahan skenario hati Ikhsan dan Dini. Satu hati berharap buahnya banyak supaya ada alasan antar-mengantar. Sementara hati yang lain berharap ada ketukan pintu dari sekeranjang mangga.
“Kok kamu lagi yang bukain pintu? Emang gak ada orang lain di rumah ini?”
“Kok kamu lagi yang nganterin mangga? Emang gak bisa nyuruh orang lain? Pake kurir kek..”
Ikhsan tersenyum-senyum sendiri melihat Dini yang cemberut diserang balik.
“Kenapa senyum-senyum? Jangan naksir ya!”
“Naksir? Kamu tuh yang naksir! Pake alasan kirim mangga terus. Buahnya kan tinggal dikit. Jangan-jangan ini beli di pasar.”
“Ya ampuun, nggak penting banget pikirannya. Udah ah, permisi.”
Makasih ya, ucap Ikhsan dalam hati. Dini sudah kabur seperti biasa. Dia masih senyum-senyum sendiri sambil memeluk keranjang. Dadanya berbunga-bunga mangga. Dini pun demikian, begitu sampai di rumahnya, bibirnya langsung mengembang senyum. Senyum semanis jus kuini yang mandi susu.
Sebulan lewat, perasaan benci makin berubah jadi suka di hati Ikhsan dan Dini. Sama-sama mulai membaca getaran ini. Saling meledek di halaman belakang menjadi babak yang ditunggu-tunggu oleh keduanya. Walaupun saling mengusili, mereka saling menyimpan senyum di balik tembok pagar. Hanya pohon mangga yang menyaksikan gengsinya mereka itu.
Suatu siang ketika pulang sekolah, mereka berpapasan di pintu pagar yang letaknya bersisian. Kali itu Ayah Dini kebetulan pulang dan ikut berpapasan dengan mereka.
“Halo, Om.”
“Halo. Wah, kalian baru pulang juga rupanya.”
“Nak Ikhsan, om minta maaf ya. Tukang kebunnya belum dapet.”
“Oh, nggak apa-apa kok, Om.”
“Bukan begitu, Om jadi tidak enak. Sabtu ini Om sudah minta tolong Dinas Kebersihan?”
“Buat apa, Ayah?”
“Karena kelamaan nggak dapet tukang kebun, mending pohon mangganya ditebang aja.”
Ikhsan dan Dini saling berpandangan dengan wajah serius.
“JANGAN!!”
Mereka berkomentar lantang. Serempak tanpa sengaja. Keduanya tersipu malu lalu buru-buru membuang muka ke arah lain. Raut muka Ayah Dini tampak bingung.
Seolah mendengar percakapan itu, pohon mangga di belakang rumah seketika bergetar menggugurkan dedaunannya. Berdesir tanpa angin.
Jika cinta di dunia ini terlahir dari sebutir apel, mungkin bagi Ikhsan dan Dini, cinta itu datang dari sekeranjang buah mangga, lengkap dengan pohon dan sampah-sampahnya!
Jakarta, Mei 2013.