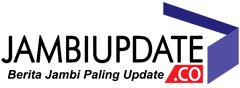Syarat 30 % kuota keterwakilan politik perempuan kembali digaungkan dalam rezim sistem Pemilu 2014 melalui Undang-Undang No.8 Tahun 2012. Banyak pro dan kontra dikeluarkan terkait syarat ini. Alasan terbesar adalah bahwa sulit bagi partai politik untuk memenuhi syarat tersebut terutama untuk daerah-daerah pelosok Indonesia. Selebihnya berbagai pihak terutama kaum laki-laki, menyangsikan akan kemandirian, kecakapan, dan kemampuan, serta daya juang perempuan untuk terjun di bidang politik bersama dengan kaum laki-laki lewat syarat tersebut yang dianggap memanjakan kaum perempuan.
Namun, terlepas dari itu, keterwakilan politik perempuan dan perlakuan khusus sementara atau lebih dikenal dengan Affirmative Action, adalah sebuah keniscayaan. Pertama, karena Indonesia telah menandatangani Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskrimansi Terhadap Perempuan (CEDAW) dan telah meratifikasinya ke dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang hal yang sama. Jika demikian, secara otomatis, Indonesia telah dikenakan segala kewajiban yang terdapat dalam muatan materi konvensi tersebut. Dalam hal ini, dasar hukumnya adalah pasal 4 CEDAW yang berisi Affirmative Action dan Bagian II Pasal 7 butir (a) CEDAW yang berisi tentang kehidupan politik dan kehidupan kemasyarakatan perempuan.
Kedua, dinamisasi kehidupan perempuan yang telah merambah dan mendukung berbagai sektor, apalagi dibidang ekonomi. Separuh lebih penduduk dunia adalah perempuan yang merupakan target potensial pemasaran dan murahnya tenaga kerja, serta berkembangnya industri keratif. Ironisnya, masalah-masalah sosial kemasyarakatan secara psikologis dan ekonomi seperti kemiskinan, kesehatan, keterbelakangan, pendidikan, kriminalitas, juga merupakan jerat utama dalam jejaring separuh lebih penduduk dunia yang adalah perempuan itu. Sementara itu, perempuan juga diandalkan untuk menanggung beban keberlangsungan eksistensi kehidupan melalui proses reproduksi biologis dan penjagaannya terhadap generasi penerus berikut masa depannya.
Oleh karena itu, berbagai pihak, terutama kaum perempuan sendiri, tidak bisa lagi untuk menutup mata melihat kondisi yang ada. Selain sebuah keniscayaan, keterwakilan politik perempuan adalah tangga darurat bagi kaum perempuan untuk menghadapi situasi genting yang setiap saat bisa saja menimpa diri semua perempuan dan berimbas kepada kelangsungan hidup keluarganya terutama anak-anaknya. Ini mengingat, bahwa pada situasi yang paling tidak menguntungkan, perempuanlah yang akan paling menderita dibanding dengan kaum laki-laki.
Namun, terlepas dari itu, keterwakilan politik perempuan dan perlakuan khusus sementara atau lebih dikenal dengan Affirmative Action, adalah sebuah keniscayaan. Pertama, karena Indonesia telah menandatangani Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskrimansi Terhadap Perempuan (CEDAW) dan telah meratifikasinya ke dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang hal yang sama. Jika demikian, secara otomatis, Indonesia telah dikenakan segala kewajiban yang terdapat dalam muatan materi konvensi tersebut. Dalam hal ini, dasar hukumnya adalah pasal 4 CEDAW yang berisi Affirmative Action dan Bagian II Pasal 7 butir (a) CEDAW yang berisi tentang kehidupan politik dan kehidupan kemasyarakatan perempuan.
Kedua, dinamisasi kehidupan perempuan yang telah merambah dan mendukung berbagai sektor, apalagi dibidang ekonomi. Separuh lebih penduduk dunia adalah perempuan yang merupakan target potensial pemasaran dan murahnya tenaga kerja, serta berkembangnya industri keratif. Ironisnya, masalah-masalah sosial kemasyarakatan secara psikologis dan ekonomi seperti kemiskinan, kesehatan, keterbelakangan, pendidikan, kriminalitas, juga merupakan jerat utama dalam jejaring separuh lebih penduduk dunia yang adalah perempuan itu. Sementara itu, perempuan juga diandalkan untuk menanggung beban keberlangsungan eksistensi kehidupan melalui proses reproduksi biologis dan penjagaannya terhadap generasi penerus berikut masa depannya.
Oleh karena itu, berbagai pihak, terutama kaum perempuan sendiri, tidak bisa lagi untuk menutup mata melihat kondisi yang ada. Selain sebuah keniscayaan, keterwakilan politik perempuan adalah tangga darurat bagi kaum perempuan untuk menghadapi situasi genting yang setiap saat bisa saja menimpa diri semua perempuan dan berimbas kepada kelangsungan hidup keluarganya terutama anak-anaknya. Ini mengingat, bahwa pada situasi yang paling tidak menguntungkan, perempuanlah yang akan paling menderita dibanding dengan kaum laki-laki.
Dalam kerangka Affirmative action, syarat 30 % kuota keterwakilan politik perempuan, adalah sebuah upaya untuk menuju percepatan tercapainya persamaan pemenuhan hak antara laki-laki dan perempuan di bidang politik. Tapi sekali lagi, memang untuk menjalankan upaya ini tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, dikarenakan posisi inferior perempuan dan ketidak percayaan publik terhadap kredibiltas perempuan untuk terjun ke ranah politik secara pribadi dan mandiri, bukan atas pengaruh bayang-bayang atau embel-embel nama besar suami juga keluarga.
Menyikapi hal tersebut, penulis berpendapat, bahwa adalah wajar jika partai politik peserta pemilu 2014 dalam pemenuhan syarat 30 % kuota keterwakilan politik perempuan, banyak memunculkan daftar nama calon legislatif (caleg) perempuan yang bernuansa politik dinasti. Berdasarkan pengamatan, caleg perempuan yang muncul kebanyakan merupakan istri dari pejabat publik tertentu, atau istri dari petinggi partai, yang suaminya incumbent.
Kondisi ini tidaklah perlu dipermasalahkan dulu untuk langkah awal upaya pemenuhan 30 % kuota keterwakilan politik perempuan. Alasan yang dapat penulis berikan adalah, pertama; kuantitas merupakan target pertama yang harus dikejar untuk memotivasi kesadaran politik perempuan akan pentingnya keterwakilan kaumnya. Kedua; medan politik yang semakin rumit dan berat menuju pemilu 2014, merupakan sarana pembelajaran perempuan untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman berharga dibidang politik. Ketiga; kebangkitan kesadaran politik kaum perempuan , paling mudah dapat dimulai dari kaum elit dengan tangga dinastinya. Ini dengan mengingat, sumber daya, koneksi, jaringan, dukungan suara, dan segala akses kemudahan yang mendukung mereka untuk bergerak cepat dalam arena pertempuran perebutan kekuasaan.
Memang kesannya jika pemenuhan syarat 30 % kuota keterwakilan politik perempuan digulirkan dari tangga politik dinasti, kualitas seolah diabaikan dengan posisi sang wakil perempuan yang hanya sebagai boneka pajangan mudah di steer. Tetapi kedepan, penulis yakin, perempuan-perempuan dalam politik dinasti yang diterjunkan untuk mewakili syarat keterwakilan politik kaumnya itu, akan berada dalam titik jenuh kondisi kesadarannya, bahwa posisi mereka merupakan hal yang penting dan signifikan untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak dirinya juga kaumnya, berdasarkan fakta-fakta mereka temui nantinya selama dilapangan dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil politik kaumnya, dan juga benturan-benturan kekuasaan yang kerap mereka temui dalam arena politis bisa jadi melelahkan sekaligus menggelisahkan kesadaran mereka.
Harapannya, setelah posisi keterwakilan politik perempuan ini berjalan mapan secara kuantitas meskipun dibidani dengan munculnya wakil politik perempuan dari tangga politik dinasti secara acak dan paksa, perempuan-perempuan itu dapat menjadi cermin, teladan, motivator bagi pemberdayaan politik perempuan dibawahnya terutama di tingkat grass root. Selanjutnya stakeholder yang bersentuhan dengan wakil politik perempuan itu, dapat lebih banyak memberikan dorangan dan bimbingan tekhnis untuk upgrade kuantitas menjadi kualitas ,melalui kerjasama yang dapat dibangun dengan partai kendaraan pengusung wakil poltik perempuan atau melalui pintu parlemen.
Tak hanya itu, juga upaya membangun kesadaran wakil politik perempuan tersebut untuk membentuk jaringan tidak hanya ditingkat parlemen tapi sampai ke grass root untuk eksistensi posisi mereka sebagai wakil politik dan juga regenerasi. Lebih penting lagi adalah, setelah terbentuknya upgrade dan jaringan, upaya saling sharing atau tukar pengalaman serta strategi mengenal dan menghadapi medan pertempuran politik harus berjalan, agar jejaring keterwakilan politik perempuan menjadi solid dan kuat. Setelahnya, publik tinggal menilai kemampuan dari wakil politik perempuan tersebut ketika masih dalam bayang-bayang penuh embel-embel dinastinya, dan setelah mengalami upaya pemberdayaan sedemikian rupa.
*Penulis adalah dosen di jurusan Ilmu Pemerintahan dan merupakan Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Nurdin Hamzah Jambi, juga anggota Komunitas Penulis Jambi, Pelanta.
Menyikapi hal tersebut, penulis berpendapat, bahwa adalah wajar jika partai politik peserta pemilu 2014 dalam pemenuhan syarat 30 % kuota keterwakilan politik perempuan, banyak memunculkan daftar nama calon legislatif (caleg) perempuan yang bernuansa politik dinasti. Berdasarkan pengamatan, caleg perempuan yang muncul kebanyakan merupakan istri dari pejabat publik tertentu, atau istri dari petinggi partai, yang suaminya incumbent.
Kondisi ini tidaklah perlu dipermasalahkan dulu untuk langkah awal upaya pemenuhan 30 % kuota keterwakilan politik perempuan. Alasan yang dapat penulis berikan adalah, pertama; kuantitas merupakan target pertama yang harus dikejar untuk memotivasi kesadaran politik perempuan akan pentingnya keterwakilan kaumnya. Kedua; medan politik yang semakin rumit dan berat menuju pemilu 2014, merupakan sarana pembelajaran perempuan untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman berharga dibidang politik. Ketiga; kebangkitan kesadaran politik kaum perempuan , paling mudah dapat dimulai dari kaum elit dengan tangga dinastinya. Ini dengan mengingat, sumber daya, koneksi, jaringan, dukungan suara, dan segala akses kemudahan yang mendukung mereka untuk bergerak cepat dalam arena pertempuran perebutan kekuasaan.
Memang kesannya jika pemenuhan syarat 30 % kuota keterwakilan politik perempuan digulirkan dari tangga politik dinasti, kualitas seolah diabaikan dengan posisi sang wakil perempuan yang hanya sebagai boneka pajangan mudah di steer. Tetapi kedepan, penulis yakin, perempuan-perempuan dalam politik dinasti yang diterjunkan untuk mewakili syarat keterwakilan politik kaumnya itu, akan berada dalam titik jenuh kondisi kesadarannya, bahwa posisi mereka merupakan hal yang penting dan signifikan untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak dirinya juga kaumnya, berdasarkan fakta-fakta mereka temui nantinya selama dilapangan dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil politik kaumnya, dan juga benturan-benturan kekuasaan yang kerap mereka temui dalam arena politis bisa jadi melelahkan sekaligus menggelisahkan kesadaran mereka.
Harapannya, setelah posisi keterwakilan politik perempuan ini berjalan mapan secara kuantitas meskipun dibidani dengan munculnya wakil politik perempuan dari tangga politik dinasti secara acak dan paksa, perempuan-perempuan itu dapat menjadi cermin, teladan, motivator bagi pemberdayaan politik perempuan dibawahnya terutama di tingkat grass root. Selanjutnya stakeholder yang bersentuhan dengan wakil politik perempuan itu, dapat lebih banyak memberikan dorangan dan bimbingan tekhnis untuk upgrade kuantitas menjadi kualitas ,melalui kerjasama yang dapat dibangun dengan partai kendaraan pengusung wakil poltik perempuan atau melalui pintu parlemen.
Tak hanya itu, juga upaya membangun kesadaran wakil politik perempuan tersebut untuk membentuk jaringan tidak hanya ditingkat parlemen tapi sampai ke grass root untuk eksistensi posisi mereka sebagai wakil politik dan juga regenerasi. Lebih penting lagi adalah, setelah terbentuknya upgrade dan jaringan, upaya saling sharing atau tukar pengalaman serta strategi mengenal dan menghadapi medan pertempuran politik harus berjalan, agar jejaring keterwakilan politik perempuan menjadi solid dan kuat. Setelahnya, publik tinggal menilai kemampuan dari wakil politik perempuan tersebut ketika masih dalam bayang-bayang penuh embel-embel dinastinya, dan setelah mengalami upaya pemberdayaan sedemikian rupa.
*Penulis adalah dosen di jurusan Ilmu Pemerintahan dan merupakan Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Nurdin Hamzah Jambi, juga anggota Komunitas Penulis Jambi, Pelanta.