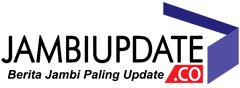Oleh : Azrul Ananda
Seorang anak kecil berlari tanpa arah. Menyenggol meja, menjatuhkan gelas. Air dan pecahannya ambyar ke mana-mana. Itu anak Indonesia. Anak orang Jawa. Dia pun bilang: "Lho, gelasnya jatuh."
Ayah kedua saya, John R. Mohn, menjadi saksi itu saat di Indonesia. Kebetulan, karena dia master jurnalistik, dia dulu belasan kali datang ke Indonesia, keliling dari Aceh sampai Papua, untuk membantu ayah beneran saya. Bisa setahun dua kali. Kebetulan dia juga pengusaha media kecil di Amerika, sekaligus akademisi.
Rupanya, ucapan sederhana anak kecil itu begitu menggelitik buatnya. Dia pun langsung mengajak saya --waktu itu masih belum usia 20 tahun-- untuk diskusi.
"Rully (panggilan dia untuk saya waktu itu), itu beda sekali dengan keluarga dan anak-anak di Amerika. Kalau di sana, kalau menjatuhkan gelas, sang anak akan bilang, 'Ups, saya menjatuhkan gelas.' Dan orang tua pada umumnya akan mengajarkan anak-anaknya bicara seperti itu," ucap John, yang awalnya menampung saya sebagai siswa pertukaran SMA di Kansas.
John minta saya merenungi dua respons itu.
"Lho, gelasnya jatuh."
"Ups, saya menjatuhkan gelas."
Yang pertama seolah itu kejadian alam. Tidak ada yang salah. Habis itu gimana, ya terserah. Mungkin akan ada yang membantu membereskan.
Yang kedua langsung tegas menyatakan kalau dia yang salah. Bukan orang lain. Seolah setelah itu siap dimarahi atau disuruh bertanggungjawab.
Sampai hari ini, cerita John itu begitu menancap di kepala. Menjadi bahan acuan ketika melihat tingkah/atau kelakuan anak sendiri, anak orang lain, anak buah, atau orang-orang lain di sekeliling. Karena dari reaksi respon pertama itu, kita bisa menilai pola pikir seseorang.
Itu dari ayah kedua.
Pelajaran dari ayah beneran lebih ekstrem.
Bukan rahasia, saya sebenarnya tipe yang gampang "naik." Apalagi kalau di kantor. Paling tidak tahan kalau ada kesalahan fundamental/sederhana, yang seharusnya tidak perlu terjadi.
Dulu juga sangat tidak sabaran. Paling sebal kalau sesuatu bisa dilakukan dengan cepat, tapi tidak bisa terjadi karena terbentur orang lain.
Saya sering mengomel ke Abah. Kadang marah-marah ke Abah. Pernah banting barang di depannya. Tidak tahan, kenapa seseorang yang punya jabatan tinggi itu tidak segera diganti. Apalagi kalau kemudian terbukti apa yang saya omelkan itu benar.
Tapi Abah itu orangnya dahsyat. Dia justru membiarkan saya membentur-bentur dinding atau atap. Toh kadang mungkin saya tidak benar, atau belum benar. Dan kalau dibiarkan, dia pasti tahu kalau mau tidak mau saya pasti harus mencari cara atau siasat untuk mendapatkan apa yang saya mau. Termasuk dengan cara harus berkolaborasi dengan orang yang saya omeli.
Mungkin itu sebabnya saya baru diangkat jadi direktur setelah 12 tahun nabyak-nabyak di kantor. Tidak langsung jadi direktur seperti anak orang lain. Wkwkwkwk...
Dan kayaknya pelajaran seperti itu yang membuat orang-orang binaan Abah banyak yang sukses. Kalau saya? Walau saya merasakan manfaatnya, saya sendiri rasanya masih work in progress. Wkwkwk...
Untungnya. Waktu saya sering marah-marah itu, belum ada media sosial dan kamera di handphone belumlah sesuatu yang umum. Wkwkwk lagi...
Sekarang kembali ke dunia sekarang.
Ketika kali pertama si virus mulai merepotkan Indonesia, terus terang saya waktu itu punya kekhawatiran yang sama dengan kebanyakan. Yaitu apakah negara kita mampu menghadapi dan menemukan jalan melewati krisis sebesar ini. Kalau negara besar dan maju saja kelabakan, kita bagaimana?
Kemudian saya punya kekhawatiran lebih jauh. Ini berkaitan dengan tren sosial politik belakangan, di mana segala keputusan dan tindakan seolah berdasarkan pencitraan. Bahwa dampak citra lebih baik dari dampak real. Bahwa kelihatan kerja itu lebih penting dari kerja beneran.
Saya khawatir, semua solusi krisis adalah solusi pencitraan.
Bukan solusi praktis cepat yang efektif, jelas, dan tegas.
Misalnya. Menyemprot disinfektan pakai drone itu keren sekali. Tapi apakah itu benar-benar efektif? Membuat robot membantu pekerja medis itu inovasi top, tapi apakah bisa dibuat dalam jumlah masal dalam waktu dekat dengan harga masuk akal sehingga bisa segera membantu sekarang juga?
Lalu urusan menutup sebuah wilayah. Beritanya heboh jalan utama diperiksa dan dijaga. Tapi sudah bukan rahasia, ada banyak jalan kecil lain yang terbuka menganga lowong bebas hambatan. Media tak pernah membahas, tapi semua orang sudah tahu sama tahu.
Masalahnya lagi, krisis seperti ini butuh kolaborasi semua pihak. Bukan hanya pejabat dan pemerintahnya. Apalagi kita bukan Tiongkok, yang bisa "main kayu" dalam membuat kebijakan. Atau negara maju lain, yang bisa "semprot uang" untuk meredam masalah teknis maupun sosial.
"Solusi pencitraan" ini bisa menyebar dilakukan semua elemen.